Ada semacam keyakinan yang berkobar bahwa puisi adalah sebuah entitas hasil dari proses perenungan yang dalam, yang mengusung “nilai-nilai”. Maka dari itu, puisi harus terbebas dari segala macam anasir yang berdiri di luar penciptaan dirinya, yang mungkin akan mengontaminasi wilayah subtil yang (hendak) dijejakinya. Di sini, dalam kapasitasnya yang mengusung “nilai-nilai” itu, puisi membangun suatu tatanan dimensional untuk memanifestasikan realitas manusia lewat representasi (model tanda) bahasa, kata-kata, yang pada gilirannya ini diharapkan akan mampu mentransformasikan, paling-tidak di tingkat afeksi-empati, “nilai-nilai” yang tersimpan pada dirinya ke wilayah yang lebih konkret. Dengan kata lain, pada titik itu, puisi akan menjelma sebagai “nilai” itu sendiri.
Heroik sekali! Saya sungguh tak akan segan untuk angkat topi pada seorang penyair yang kuat untuk bersitahan dengan keyakinan semacam ini. Ya, karena sayangnya, untuk bisa kukuh dengan “keyakinan luhur” demikian, pada saat ini sepertinya (hanya) merupakan utopia yang, meskipun tidak terlalu berlebihan, sedikit berbau kenes-naif-sentimentil; sebaris romantisme masa lalu, mungkin ketika puisi (atau sastra) hadir dalam wujudnya sebagai media pengkabar anonim yang, paling-tidak, jauh dari prasangka-prasangka eksistensialisme atau demarkasi lahan publik untuk sepiring nasi. Wallahualam.
Sepanjang yang saya amati, meskipun boleh jadi ini baru hanya pengamatan sepihak, dalam konteks kekinian puisi tampaknya tidak melulu hadir karena adanya dorongan inner-power yang muncul dari dalam diri sang penyair sebagai reaksi atas realitas yang mesti dihadapi dan disikapinya. Namun, agaknya, di sisi ini sudah harus mau diakui pula jika sebagian besar puisi kita, terutama yang kemudian dipublikasikan di media massa, telah masuk ke dalam jaring-jaring sistem produksi khas kapitalis yang memperhitungkan “untung-rugi”.
Boleh jadi, sistem semacam ini pun merupakan suatu bentuk perwujudan dari insting kreatif manusia ketika dirinya dihadapkan pada realitas yang menuntut untuk tidak lagi dipandang dan disikapi secara parsial, namun harus ditempatkan secara integral dalam konteks lingkaran dialektik yang, meskipun mungkin, “dipaksa” untuk bisa menciptakan suatu ekuilibirium, relasi-relasi harmonis yang harapannya dipandang ideal. Di sini saya lebih cenderung untuk menyebutnya “dipaksa” karena, pada kenyataannya, tidak banyak pilihan lain yang bisa dilingkari ketika keintegralannya itu masih terpusat (atau dipusatkan) pada satu bentuk kekuatan tertentu, yang dalam konteks keindonesiaan kita hari ini, pilihannya itu tampak lebih condong untuk meminang “rezim ekonomi”.
Secara sadar atau tidak, puisi (atau sastra pada umumnya) telah bergerak masuk ke dalam diskursus semacam ini. Kesan paling awal yang tampak secara permukaan adalah munculnya kecenderungan untuk mulai mengompensasikan puisi dengan tuntutan tertentu, yang bukan dalam pretensi “bentuk” atau “isi” yang terusung oleh struktur intrinsiknya, atau tendensi akan “idealisasi nilai” yang harus dipertaruhkan kemudian lewat kapasitas ekstrinsik yang dibangunnya; melainkan tuntutan yang lebih dibebankan pada relasi yang berkenaan dengan diskursus ekonomi tadi. Bahwa, persoalan yang banyak dipertanyakan kemudian tampaknya bukan lagi pada tatanan, “bilakah puisi yang ditulisnya itu akan mampu bertahan (dan hidup) dalam masyarakat-sosialisasinya?”; tetapi, “bagaimana ia (seorang penyair) harus bisa hidup dari puisi-puisinya?”
Pengamatan terhadap gejala yang berkembang dalam “sastra Indonesia modern” sebagaimana yang dilakukan oleh Will Derks, seorang pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Rijks Leiden, (tengok esainya, Pengarang Indonesia sebagai Tukang Sastra, Kalam edisi 11, 1998, h.90-100), dalam kaitannya dengan perbincangan kita ini agaknya menjadi menarik untuk disinggung kembali. Di sana Derks secara tegas menyebut bahwa para pelaku sastra di Indonesia lebih mirip “tukang” (yang menghasilkan barang kerajian) daripada “seniman” (yang menghasilkan karya seni)–kendatipun dengan catatan, istilah “tukang” dan “seniman” yang dipakainya ini ditarik dari perspektif Barat. Ia mencermati adanya kemungkinan jika sebagian besar cerpen dan puisi di media massa (termasuk sayembara menulis dan pembacaan puisi) yang di Indonesia jumlahnya begitu melimpah, merupakan hasil semacam “kerajinan gabung-menggabung” (art combinatoria) yang mampu menciptakan teks yang tak terbatas jumlahnya, sama struktur dan bentuknya, tidak dimaksudkan untuk menggapai keabadian, dan tidak pernah sama sekali baru.
Pada kasus ini, secara tidak langsung Derks menunjuk bahwa gejala tersebut bisa muncul karena ada wujud keterlibatan masal dalam kegiatan bersastra di Indonesia, yang salah satunya dicirikan dengan cerpen dan puisi yang dijadikan komoditas yang dapat dipasarkan; dijadikan alat untuk memperoleh uang dengan cepat karena media massa yang menampungnya (atau dalam sayembara) kadang-kadang memberi honorarium yang cukup besar. Derks pun mendukung alasannya ini dengan menyodorkan contoh saat Radio Nederland seksi Indonesia mengadakan sayembara penulisan; hanya dengan sekali iklan, panitia telah menerima lebih dari 2000 kiriman tulisan dari Indonesia–yang dalam asumsi Derks hal ini berhubungan dengan hadiah, yang untuk juara ketiganya saja sudah melebihi gaji bulanan pegawai negeri Indonesia.
Pertanyaannya sekarang, bermasalahkan gejala seperti itu? Boleh jadi, hal ini memang dilematis. Di satu sisi, dengan tuntutan yang ditekankan demikian akan bisa membawa konsekuensi tersendiri; sangat mungkin akan ada semacam pengabaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan karya yang kemudian dihasilkan yang sifatnya substansial, misalnya. Namun di sisi lain, terlebih jika kemudian kita kaitkan dengan budaya-ekonomi kita hari ini, tuntutan seperti itu boleh menjadi suatu hal yang dipandang cukup wajar. Bagaimanapun, bagi seorang penyair, terlebih jika kepenyairan kemudian dijadikan sebagai modal dasar untuk mempilari kehidupannya, ia akan dituntut untuk bisa berbuat lebih dalam proses kerja kreatifnya.
Kerja kreatif yang saya maksud di sini, bukan hanya dalam soal kepekaan atau problem teknis-estetis belaka; bahwa karena kreativitas yang kemudian menjadi pilar hidupnya ini pada akhirnya harus bergerak dalam arus industri kapitalistik, sebagai konsekuensi logis dari pilihannya―entah itu memang diniatkan atau justru karena terpaksa―untuk turut berpartisipasi dalam diskursus tersebut, keberadaannya pun paling-tidak harus bisa diseimbangkan dengan konstelasi kompleks di sekelilingnya, kendatipun sadar, di sini ia mungkin akan dipaksa pula untuk rela mengikuti sederet aturan dari prinsip-prinsip (ekonomi) yang berlaku di dalamnya. Sebagai contoh sederhana, bahwa karena dalam berpuisi pun ternyata membutuhkan semacam cost production (dalam pengertian real) sebagaimana halnya suatu sistem produksi dalam sebuah industri, meskipun pada awalnya mungkin bukan merupakan tujuan utama, tapi adalah menjadi wajar pula jika kemudian ada semacam pengharapan untuk mendapatkan hasil selisih lebih atau, setidaknya, tetap mengupayakan untuk mencapai break even point agar ongkos produksinya itu bisa tertutupi.
Kedengarannya mungkin menjadi begitu materialistis. Akan tetapi, adalah bukan suatu hal yang harus dipandang tabu kalaupun kemudian ada yang sampai berhitung seperti itu; dan sastra, sebagai institusi yang mengusung “nilai-nilai”, tidak perlu pula harus “merasa terluka” karenanya. Sementara, secara langsung atau tidak, kondisi semacam ini pun didukung pula oleh industri media, terutama media (massa) cetak.
Di sisi ini, media massa yang pada akhirnya menjadi sarana pengkabar (dan sekaligus market) bagi sebagian besar produk puisi yang dihasilkan oleh para penyair yang mencoba untuk menyosialisasikannya, bergerak pula dalam diskursus yang sama; berdiri dengan bersandar pada dinding kapitalistik, yang mau tidak mau menuntut untuk memandang dan menyikapi segala hal yang berkenaan dengan dirinya dalam relasi sebagaimana halnya “pasar” dan “barang belanjaan”. Alih-alih, ketika muncul gejala adanya wujud keterlibatan massal dalam kegiatan bersastra di Indonesia, karya sastra menjadi komoditi, sebagaimana yang diamati Derks, justru tidak melibatkan keberadaan dan konteks media massa yang dalam iklim kesusastraan di Indonesia begitu mendominasi, mendeterminasi, bahkan lebih dari itu, ia seakan-akan menjadi satu-satunya sarana publikasi bagi bagi karya-karya sastra yang dihasilkan (karya-karya sastra yang dibukukan pun pada kenyataannya sebagian besar terlebih dulu pernah dipublikasikan di media massa).
Sedangkan hal yang berkenaan dengan komoditi itu sendiri, persoalan market yang kemudian bergulir pun agaknya tidak (pernah) ditentukan pula oleh hukum supply and demand yang implikasinya kemudian adalah dengan harga produk yang ditawarkan; ia seakan tidak memiliki bargaining position yang kuat untuk berhadapan dengan rezim kapitalis yang bertendensi profit-lose itu. Sehingga, konon, seringkali ada karya yang bagus namun harus rela tergusur atau tertunda pemuatannya karena ia dianggap tidak memiliki proper name guaranteed yang “laku dijual”, atau bahkan karena alasan ruangnya harus diwakafkan untuk iklan. Dengan kata lain, di sini penyair (sastrawan) agaknya masih harus selalu berada dalam posisi sebagai subjek yang tersubordinasi.
Dengan konstelasi seperti itu, maka sebenarnya menjadi cukup sulit untuk bisa mengidentifikasi mana yang merupakan “produk kerajinan” dan mana yang merupakan “produk kesenian”; kerja antara “seorang tukang” dengan “seorang semiman” menjadi bias, sangat tipis garis pemisahnya ketika berhadapan dengan realitas semacam itu. Kalaupun pada akhirnya karya sastra dijadikan sebagai suatu komoditi dengan pempertimbangkan “kalkulasi ekonomis”nya, bagi seorang penyair, persoalannya barangkali hanyalah tinggal, apakah hal itu akan ia lakukan dengan tetap mempertahankan “tujuan kultural dan moral” pada karya-karya yang dihasilkannya, serta bisa menempuh semua itu dengan cara “konstitusional-prosedural-fair play” atau tidak. Saya pikir, hal ini setidaknya akan bisa dipakai untuk mengukur, apakah ia hanya sekadar “seorang tukang” atau berperan sebagai “seorang seniman”.
Barangkali memang akan tetap problematis, membuahkan ekses-ekses tertentu, kontra-indikasi, bahkan masalah-masalah baru ketika “paradigma ekonomis” semacam itu turut dilibatkan sebagai variabel eksternal di wilayah proses kerja kreatif; tidak tertutup kemungkin akan muncul konotasi negatif pada nilai “kompromis” di sini (kendatipun itu lebih dimaksudkan sebagai usaha untuk “membaca medan wacana”), agak naif kalaupun hanya disebut sekadar “siasat”, sementara masih terlalu anggun pula untuk mengidentifikasikan bahwa berpikir dalam paradigma demikian adalah “profesionalisme”. Yang jelas, ini adalah kondisi real yang mesti dihadapi: bahwa, Indonesia kita pada hari ini masih belum merupakan rumah yang nyaman bagi para penyair/sastrawan yang berkenan untuk total dalam berkarya dan terus berkarya tanpa perlu untuk merasa cemas dihantui “dunia sembako” yang akan melilitnya; atau dengan retorika hiperbola, “di negeri ini, masih butuh 1000 puisi untuk 1 bungkus nasi”.
²²²
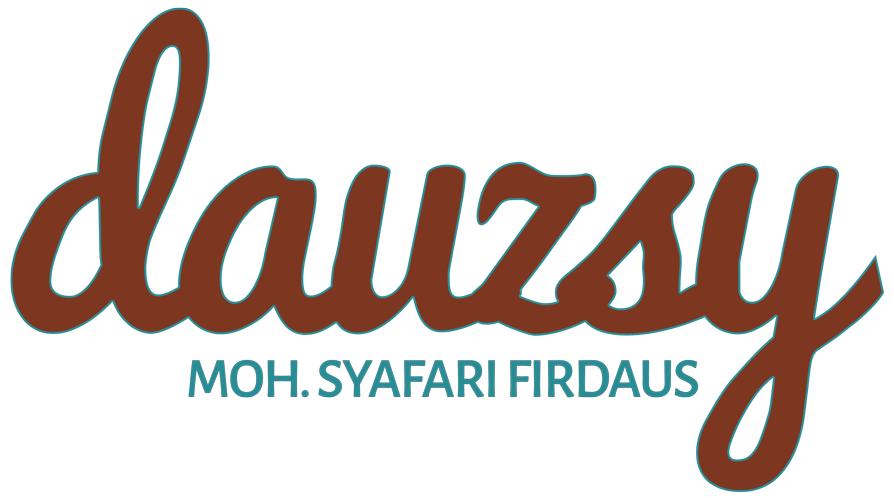

3 komentar
Boss, inget keneh ka sayah? Pernah di gsstf tapi nepi ka ayeuna angger teu ngarti seni 🙂
Wilujeng ah, sering maca tulisanana di koran.
Tata
http://bukamulut.blogspot.com
hehe. tentu saja saya masih inget atuh :p
da meureun seni mah memang teu kudu dimengerti. keun we sina “nyungsep sakahayangna”. sugan isuk jaganing geto manggih “padumukanana”. jigana mah kitu. da sarua we sayah ge, nepi ayeuna can manggih jawab nu teges, seni teh naon. huehuehue…
di mana ayeuna? konon, kabarnya, geus jadi english transleter kahot? :d masih di buah batu?
Bwuahaha.. sugan teh poho.. Kaingetan, pernah ningali Acep di STV, jadi dosen ITB nya? Resep lah ningali sarukses.. Sayah nyeceb di lembur ayeuna mah, di Panjalu.
Heheh..penerjemah kapaksa, bakat ku butuh..