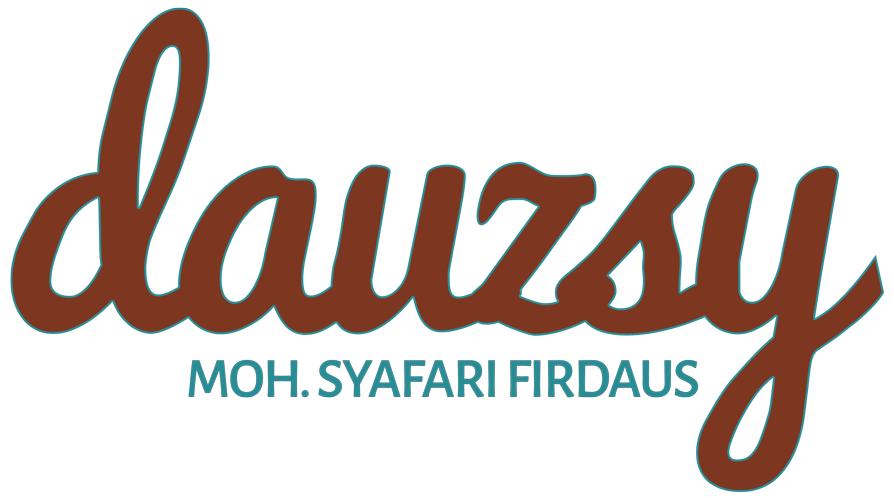Sekadar Catatan:
Di dalam lakon ini, sesungguhnya boleh terjadi sejumlah peristiwa. Dari sejumlah peristiwa yang ada, satu sama lain boleh jadi tidak menampakkan persinggungannya sama sekali. Demikianlah Blues untuk Ayah: di tingkat tekstual, lakon ini hanya berusaha untuk mengumpulkan serpihan peristiwa yang di dalamnya mengandaikan ada kaitan relasi, yang dalam hal ini ditunjukkan lewat “narasi tentang ayah”. Mungkin mirip dengan kolase, meski saya sendiri lebih cenderung untuk menyebutnya sebagai usaha penyatuan dua monolog yang berbicara tentang “ayah” dalam satu panggung.
Tokoh :
- Seorang laki-laki bernama Aziz Manuel Lawalata
- Seorang perempuan bernama Rina Desyani Firdaus
* *
Satu
Sett panggung ditata seperlunya.
Di sana, tokoh Aziz dan Rina, berdiam dalam kesendiriannya masing-masing.Adegan dibuka dengan suara-suara. Riuh. Melengking-lengking. Pelan kemudian menguap lapat-lapat, dan seterusnya menggumpal di kejauhan. Yang tersisa dari kesunyiannya hanya tinggal suara detak halus ketukan jam dinding, keletak sepatu, derit geseran kursi dan meja, serta sebentuk suara tembakan.
Aziz sontak tercekat. Sesaat ia mengawasi sekeliling, sebelum kemudian berjalan mengendap-endap hingga menghilang dari panggung. Tak berapa lama kemudian ia muncul lagi dengan wajah cemas dan menegang. Nafasnya turun naik. Dalam kekalutannya, ia pun meradang. Berlari dari satu sisi ke sisi yang lain, seraya menceracau sendiri meski tak jelas apa yang diceracaukannya itu. Setelah berteriak, ia kembali gegas menghilang.
Waktu lewat.
Sesaat setelah Aziz pergi, Rina pelan tersenyum, lalu tertawa. Dia terus tertawa sebelum kembali pada kediamannya semula. Sesaat kemudian dia mulai menggerakkan tubuhnya, seperti memainkan sebuah tarian.
Waktu lewat. Kembali terdengar suara-suara.
Aziz muncul dengan tergesa.
Aziz Ada yang mengetuk pintu!
Untuk beberapa saat Aziz terus mengendap-endap dalam cemas dan ketegangan yang luar biasa. Ia tercekat ketika terdengar lagi sebentuk suara tembakan.
Aziz Ayah!
Rina Ayah?
Dalam kekalutannya, Aziz kembali gegas menghilang.
Rina (Tergagap ketakutan) Tidak, Ayah. Rina tidak kemana-mana. Sedari tadi Rina hanya di sini. Tak ada yang Rina lakukan selain menunggu ayah. Sungguh, ayah, Rina tidak kemana-mana. Rina hanya bermain dengan diri Rina sendiri. Seperti kata ayah, Rina—
Selang tak berapa lama, Aziz muncul lagi.
Aziz Ayah mati!
Rina Persetan! Kepiting rebus! Ayah botak! Aku muak! (diteruskan dengan serentetan ceracau yang tak jelas) Sudahlah, Rina! Kini bukan saatnya lagi bagi kita untuk memajangkan sebongkah retak yang akan kembali mengoyak wajah kita. Kapan kau akan menemuiku di sini? Kita sudahi saja percakapan tentang ayah. Ada yang akan tetap menyakitkan di sana. Sungguh, Rina. Sudah terlalu lama. Hari telah larut. Mengapa kau tak tengok saja ibu— Ibu? (berubah menjadi gelisah) Tapi aku mendapatkan ibu telah membatu di jendela itu!
Aziz Aku hanya mendapatkan ayah membiru di rumah itu. Ada yang mengetuk pintu. Ayah mati.
Aziz terus mengulang-ulang bagian akhir ucapannya: “Ada yang mengetuk pintu. Ayah mati.” Sementara Rina bergelut dengan tubuhnya yang tiba-tiba menggigil.Waktu lewat. Suara-suara itu lagi, dan sebentuk suara tembakan.
**
Dua
Prolog para tokoh
Aziz Namaku Aziz Manuel Lawalata. Kata orang-orang aku adalah anak seorang pemberontak separatis sayap kiri yang tak pernah tanggung-tanggung membunuh orang. Aku sendiri tak tahu persis apa mereka berkata benar atau tidak. Yang aku tahu, sepuluh tahun yang lalu ayahku telah mati. Demi Tuhan, mereka tak tanggung-tanggung mengeksekusinya di hadapan kami. Kepala ayah pecah, meledak. Kami ada di sana, aku dan ibu. Jelas sekali melihatnya. Entah kenapa mereka masih membiarkan kami hidup. Tapi mengapa aku masih dibiarkan hidup? Ingatan itu terlalu kental di kepalaku. Ketukan pada pintu, keletak suara sepatu, bau harum darah ayah— Tapi siapa mereka, Ibu? Kenapa di sepanjang malam itu ayah hanya bungkam?
Rina Namaku Rina. Rina Desyani Firdaus. Tapi ayah biasa memanggilku Rina yang manis. Kini aku hampir menginjak usia 19. Aku dibesarkan oleh sebuah keluarga yang terbilang mapan. Bahkan sangat berkecukupan. Aku punya— ah, aku tak pandai bercerita. Lagipula, aku tak tahu apa-apa. Aku bahkan tak mengenal siapa diriku sendiri. Ya, seperti juga diri ibu, hanya ayah yang tahu. Di sini tubuh kami seperti hanya milik ayah. Kami hanya meminjamnya dari ayah. Segalanya adalah ayah. Hanya ayah. Ayah yang— ah, aku tak pandai bercerita. Lagipula, aku takut ayah akan marah. Ibu pun telah dibuatnya membatu di jendela itu. Oleh ayah. Ya, tak ada yang menjerit saat pistol itu meletus— Maafkan aku, Ibu. Rina harus pergi. Ada bayang-bayang ganjil yang selalu merobek-robek wajahku di setiap kali aku bangun. Ada yang selalu berusaha mencocokkan wajahku dengan wajahnya, Ibu. Menjelmakan aku seperti bukan Rina sesungguhnya. Aku ingin selalu menjadi Rina. Harus menjadi Rina. Bukan siapa-siapa. Bukan ayah, bukan ibu. Aku perlu menjadi Rina. Rina harus membunuh setiap gelombang yang akan terus tenggelam dalam bayang-bayang ganjil itu. Aku perlu menjadi Rina. Agar ayah tak akan mampu lagi menyentuhku seperti pada ibu yang disekapnya dalam penjara batu. Agar ayah tak lagi menjadikan rumah ini sebagai pecahan kaca, serpihan perih, dan darah yang selalu menyembur-nyembur menguyupkan dinding itu. Aku tak ingin kuyup, Ibu. Di sini hanyalah aku, Rina. Aku adalah Rina—(suaranya makin sayup menghilang)
**
Tiga
Aziz Ayah bukan seorang pemberontak! (terus mengulang-ulang ucapannya) Ayah tidak mati sebagai pemberontak!
Rina Aku sangat ingin menjadi seorang pemberontak.
Aziz Ayah bukan seorang pemberontak!
Rina Biarkan aku menjadi seorang pemberontak. Mengajak ibu. Bersekongkol dengan ibu. Dengan Rina. Menyerbu ayah. Dor! Dor! Lalu aku akan berbahagia (lalu menari-nari kecil seraya tertawa).
Aziz (Kepada Rina) Jadi kau kah yang kulihat itu? Seseorang yang mendekati ayah, yang menggores-goreskan belati di wajahnya—
Rina (Melangkah surut) Aku?
Aziz (Memburu Rina) Bajingan! Takkan kubiarkan ayah mati!
Rina Aku— (tergagap-gagap seraya berlari ketakutan) Di sini penuh dengan mata pisau. Ada di mana-mana. Juga di mata ayah— Jangan lagi kau mendekat!
Untuk sekian saat mereka hanya saling berpandangan.
Rina (Kepada Aziz) Kau sakit? Aku, Rina― (Berulang-ulang).
Keduanya sudah begitu dekat. Ada sentuhan-sentuhan kecil, sebelum kemudian Aziz menghempaskannya.
Rina Kau sakit, Ayah!
Aziz Aku tidak peduli! Aku sudah tidak peduli dengan segala sesuatu yang semestinya aku lakukan. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menjadikan diriku seperti aku sekarang ini. Apalagi yang mesti aku risaukan?
Rina Lakukanlah!
Aziz Cuah! Bagaimanapun, aku harus tetap hidup. Setidaknya, bertahan agar aku tetap hidup. Dulu aku memang sempat berpikiran untuk mati muda. (Pelan tertawa) Tapi siapa kiranya yang ingin mati muda? Ada barangkali. Beberapa. Aku? Dengan segala hormat, tidak, terima kasih. Sampai hari ini pun aku masih butuh hidup lebih lama. Meski mungkin itu malah akan memperpanjang segala sesuatu seperti yang kini aku hadapi. Tapi tak apa. Toh aku sungguh percaya, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Segala. Mudah-mudahan, ya—
Rina Lakukanlah! (Meradang) Karena kasih Tuhan adalah ibu. Kasih ayah adalah batu! Hanya batu yang diberikan ayah untuk hidupku. Bahkan ibu pun dijadikannya batu! Kau sakit, ayah!
Aziz Aku hanya perlu tahu kenapa ayah mesti mati.
Rina Ayah harus terbunuh dalam hidupku.
Aziz Sampai hari ini, aku masih ingat betul kejadian itu. Ayah duduk di kursi dengan wajah yang memerah―
Rina Ayah memang seperti kepiting rebus!
Aziz Darah yang perlahan menetes dari hidung dan mulutnya seperti sudah tidak dirasanya lagi. Ibu tersudut di pojok ruangan sambil mendekap erat tubuhku. Beberapa kali ibu mencoba untuk berteriak. Tapi moncong pistol yang siap mengarah dan melubangi kening kami, telah membuat diri ibu kembali surut. Ibu pasti tidak ingin melihat salah satu dari kami tergeletak bermandikan darah— Begitu, Ibu? Kita memang ketakutan. Tapi tidak semestinya ayah mati. Ayah bukan seorang pemberontak― Ayah tidak mati sebagai pemberontak! (kalut) Berceritalah. Ayah pasti pernah mengatakan sesuatu pada ibu. Tidak seharusnya ibu bungkam seperti ayah. Aku harus tahu. Demi Tuhan, jangan sampai aku menelan kebungkaman demi kebungkaman yang kalian berikan di kuburku!
Rina Kau sakit, ayah! Aku, Rina. Aku— Ibu— Aku harus pergi, Ibu. Aku— Tapi ayah pun diam-diam selalu mengulang-ulang ucapannya: “Kau adalah anak termanis, Rina. (diucapkan berulang-ulang) Ayah telah siapkan seluruh perbincangan untukmu.” Apa catatan itu masih kau simpan dalam potret keluarga kita yang kini pecah menaburkan petaka?
Aziz Demi Tuhan, jangan sampai aku menelan kebungkaman demi kebungkaman yang kalian berikan itu.
Rina (Kepada Aziz) Berkali-kali ayah telah bilang, kau anak termanis, Rina. Diamlah. Jangan lagi kau menangis! Ayah akan membawamu ke mana-mana, ke tempat yang kau suka. Diamlah. Dan jangan lagi kau menangis. Sebaiknya simpan saja semua belanjaan kita ke dalam kulkas, biar segalanya membeku, dan dingin itu akan kembali menyegarkan wajahmu. Diamlah, Rina. Jangan menangis! Bukankah kau anak termanis? Kau dengar, Rina? Bawalah semua itu, masukkan seperti perintah ayahmu. Ibu pun pasti ada di sana. Sengaja ayah menyuruhnya agar ibu bisa segar kembali seperti semula. Kau dengar, Rina?
Mereka berpelukan.
Waktu lewat.
Aziz Sampai hari ini, aku masih ingat betul kejadian itu. Ayah duduk di kursi dengan wajah yang memerah. Darah yang perlahan menetes dari hidung dan mulutnya seperti sudah tidak dirasanya lagi. Ibu tersudut di pojok ruangan sambil mendekap erat tubuhku. Beberapa kali ibu mencoba untuk berteriak. Tapi moncong pistol yang siap mengarah dan melubangi kening kami, telah membuat diri ibu kembali surut. Ibu pasti tidak ingin melihat salah satu dari kami tergeletak bermandikan darah—Begitu, Ibu? Kita memang ketakutan. Tapi tidak semestinya ayah mati. Ayah bukan seorang pemberontak! Ayah tidak mati sebagai pemberontak! Berceritalah. Ayah pasti pernah mengatakan sesuatu pada ibu. Tidak seharusnya ibu bungkam seperti ayah. Aku harus tahu!
Rina Sekian lama aku telah mencoba untuk mengenali tubuh ayah. Tak ada yang berubah. Ayah yang selalu tersenyum lewat sorot matanya yang menjanjikan ketenangan laut yang tak habis mengaramkan rindu dan cintanya.
Aziz Demi Tuhan, aku— Ah, tapi kenapa pula aku harus terus memikirkannya? Oh, alangkah indahnya kalau aku tidak berpikir (tertawa). Segala persoalan mungkin akan bisa menjadi sangat lain andai saja aku tidak pernah berpikir: barangkali aku, hidupku, akan tampak indah, begitu indah, bahkan mungkin jauh lebih indah dari yang semestinya—
Rina Aku berusaha untuk menerjemahkan bahasa ayah meski itu hanya membuahkan air mata, mata pisau, dan kemarau. Lihatlah, Rina. Tubuh pucatmu hanya ditumbuhkan dari jarum jam yang diputarkan ayah dari semenjak kanak-kanak kita.
Aziz Ceracaumu bau busuk!
Rina Tak ada yang lebih busuk dari ayah!
Aziz Ayah mati. Kepalanya meledak. Kau semestinya tahu siapa mereka!
Rina Aku pun semestinya tahu di mana Rina berada.
Untuk sekian lama mereka hanya termangu.
Waktu lewat.
Sesaat, terdengar lagi suara-suara.
Aziz Ssstt! (beranjak, mengendap pelan-pelan) Ada yang mengetuk pintu!
Rina (melakukan hal serupa) Rina?
Aziz Keletak suara sepatu—
Rina Kau kah?
Aziz Bau harum darah ayah—
Rina Di sini, Rina. Aku di sini. Datanglah kau di sini. Kita sudahi saja percakapan tentang ayah. Ada yang akan tetap menyakitkan di sana.
Aziz Segerombolan malaikat maut yang dikirim Tuhan! Mau mengeroyok ayah (bahak tertawa). Tuhan, apa Kau takut kalau cuma mengirim satu saja?
Rina Aku sudah terlalu lama mencarimu, Rina. Datanglah. Persimpangan ini terlalu banyak memberikan pilihan. Aku lelah, Rina. Sungguh. Lihatlah. Bacalah apa yang kini tercatat dalam tubuhku, tubuhmu yang telanjur koyak itu. Bacalah, Rina. Kita harus menyebrangi kecemasan kita sendiri. Kita telah berpisah lama, Rina. Kita semestinya bersama, menemukan persinggahan yang sama. Sudah saatnya kini kau temui aku. Datanglah!
Lapat di kejauhan suara-suara itu: detak halus ketukan jam dinding, keletak sepatu, derit geseran kursi dan meja. Semakin riuh. Menggelombang. Melengking-lengking. Memekakkan. Sebentar sunyi; sebelum kemudian terdengar sebentuk suara tembakan lagi.
Aziz kembali sontak tercekat, namun kini ia lantas terus tertawa seraya berlari dari satu sisi ke sisi yang lain.
Aziz Kenapa tak sekalian saja Kau mengirim seribu malaikat maut untukku, Tuhan! Agar aku— Ayah— mereka— (terus tertawa)
Rina Di mana kau, Rina?
Aziz Aku tidak peduli! Aku sudah tidak peduli dengan segala sesuatu yang semestinya aku lakukan. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menjadikan diriku seperti aku sekarang ini. Apalagi yang mesti aku risaukan? Betul, bagaimanapun, aku harus tetap hidup. Setidaknya, bertahan agar aku bisa tetap hidup. Dulu aku memang sempat berpikiran untuk mati muda. Tapi siapa kiranya yang ingin mati muda? Ada barangkali. Beberapa. Aku? Dengan segala hormat, tidak, terima kasih. Sampai hari ini pun aku masih butuh hidup lebih lama. Meski mungkin itu malah akan memperpanjang segala sesuatu seperti yang kini aku hadapi. Tapi tak apa. Toh aku sungguh percaya, Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Segala. Mudah-mudahan, ya— Dan jangan lagi Kau membuatku untuk berpikir. Oh, alangkah indahnya kalau aku tidak berpikir. Segala persoalan mungkin akan sangat lain jika saja aku tak pernah berpikir: barangkali aku, hidupku, akan tampak indah, begitu indah, bahkan mungkin jauh lebih indah dari yang semestinya— Demi Tuhan, berceritalah, Ibu! Tidak seharusnya ibu bungkam seperti ayah. Jangan sampai aku menelan kebungkaman demi kebungkaman yang kalian berikan di kuburku!
Rina Ibu, aku harus pergi. Aku tak mau lagi ada di sini. Ada bayang-bayang ganjil yang selalu merobek-robek wajahku di setiap kali aku bangun. Ada yang berusaha mencocokkan wajahku dengan wajahnya, Ibu. Menjelmakan aku seperti bukan Rina sesungguhnya. Aku ingin selalu menjadi Rina. Harus menjadi Rina. Bukan siapa-siapa. Bukan ayah, bukan ibu. Aku perlu menjadi Rina. Rina harus membunuh setiap gelombang yang akan terus tenggelam dalam bayang-bayang ganjil itu. Aku perlu menjadi Rina. Agar ayah tak akan mampu lagi menyentuhku seperti pada ibu yang disekapnya dalam penjara batu. Agar ayah tak lagi menjadikan rumah ini sebagai pecahan kaca, serpihan perih, dan darah yang selalu menyembur-menyembur menguyupkan dinding itu. Aku tak ingin kuyup, Ibu. Di sini hanyalah aku, Rina. Aku adalah Rina, yang sendirian mesti mencari tempat singgahnya di mana.
**
Empat
Epilog.
Rina Aku adalah Rina. Aku harus menjadi Rina. Tapi ayah selalu memanggilku Rina yang manis. Tidak, Ayah. Rina tidak kemana-mana. Sedari tadi Rina hanya di sini, seperti kata ayah. Tak ada yang Rina lakukan selain menunggu ayah. Sungguh, ayah, Rina tidak kemana-mana. Rina hanya bermain dengan diri Rina sendiri.
Aziz Aku, Aziz Manuel Lawalata. Kata orang-orang aku adalah anak seorang pemberontak. Aku sendiri tidak pernah tahu. Hanya sampai kini aku masih mencium bau harum darah ayah. Siapa mereka, Ibu? Siapakah ayah? Kenapa semuanya hanya bungkam?
Seperti di awal pertunjukkan, Aziz dan Rina kembali berdiam dalam kesendiriannya masing-masing.
Waktu lewat. Sekali lagi sebentuk suara tembakan.
Black out.
***
bandung, gsstf―pajajaran―dd merdeka, 11/99
*] Naskah lakon/kompilasi 2 monolog ini merupakan hasil adaptasi dari cerpen Rina dan Dirinya dan Stranger In The Night karya Moh. Syafari Firdaus. Lakon ini pernah dipentaskan oleh GSSTF Unpad pada 4–5 Desember 1999. Aktor yang bermain adalah Noor Pandhit (Aziz) dan Ade ND (Rina).