DESA Alas Tlogo, Pasuruan, 30 Mei 2007, tentara versus warga. Senjata tentara kembali menyalak: empat orang tewas. Yang menjadi korban, sebagaimana biasa, rakyat jelata.
Ini bukan sekadar insiden, tapi (lagi-lagi) tragedi. Celakanya, tragedi semacam ini bukan hanya sekali-dua: tapi berulang-ulang seakan tak ada bosannya. Tragedi ini pun semakin menambah panjang daftar korban dari berbagai kasus yang bersumberkan sengketa tanah (agraria) di Indonesia.
Tragedi Pasuruan ini sungguh ironis karena selang beberapa hari sebelumnya (22 Mei 2007), Kabinet Yudhoyono baru menggelar rapat terbatas yang membahas soal reforma agraria. Selain masalah penanganan sengketa tanah, pada rapat itu pun dibahas mengenai tanah yang dialokasikan khusus untuk masyarakat miskin.
••
SENGKETA tanah (dan sumber-sumber agraria pada umumnya) sepertinya merupakan konflik laten yang setiap saat siap mengancam sebagai bom waktu. Dari berbagai kasus yang terjadi, bangkit dan menajamnya sengketa tanah tidaklah terjadi seketika, namun tumbuh dan terbentuk dari benih-benih yang sekian lama memang telah terendap. Benih-benih inilah―entah apakah “dipelihara” atau sebelumnya memang tidak terbaca― yang seterusnya potensial untuk meledak setiap saat, tanpa bisa diprediksi, sebagaimana kasus di Pasuruan yang berbuah tragedi.
Pihak-pihak yang bersengketa pun sebagian besar―kalaupun tidak bisa disebut, hampir seluruhnya―bukan hanya individual, namun melibatkan tataran komunal. Keterlibatan secara komunal inilah yang memungkinkan sengketa tanah merebak menjadi kerusuhan massal yang menelan banyak korban. Tatkala kerusuhan meledak, rakyat lah yang kerap menanggung akibat yang paling berat.
Pada konteks kasus-kasus sengketa tanah ini, kiranya bukan sekadar desas-desus jika ada cerita, negara justru kerap bersekongkol dengan para pemilik modal. Rakyat cukup diberi ilusi: semua demi negeri ini, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi repeh rapih toto tengtrem kerto raharjo. Mereka yang menolak ilusi tersebut, gampang saja solusinya: tinggal memberinya shock therapy dengan teror, intimidasi, dan tindakan refresi. Demikianlah “politik agraria” yang selama ini tampaknya terjadi.
Cerita semacam ini kiranya bukan hanya tersimpan sebagai milik Rezim Orde Baru. Di alam keindonesiaan kita hari ini yang konon tengah menyuarakan reformasi, berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan oleh (aparat) negara terhadap masyarakat masih kerap terjadi dalam konteks sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya. Sebut saja, kasus penggusuran Masyarakat Adat Meler-Kuwus, Manggarai, NTT yang dituduh telah melakukan “perampasan tanah negara” pada tahun 2002; atau kasus penangkapan dan intimidasi terhadap 8 anggota Serikat Petani Pasundan di Garut yang dituduh sebagai perambah dan perusak hutan pada awal Maret 2006.
Padahal, Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah mengamatkan bahwa “menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia” adalah salah satu prinsip yang wajib ditegakkan oleh (aparat) negara dalam penanganan sengketa agraria. Dengan merujuk pada Tap MPR ini saja, cara-cara yang ditempuh oleh (aparat) negara itu tentu saja menjadi tindakan yang tragis-ironis. Sekali lagi hal itu pun bisa menunjukkan, betapa bobroknya implementasi hukum kita, dan betapa masyarakat yang semestinya dilindungi selalu berada dalam posisi tidak berdaya, selalu dipersalahkan, dan menjadi korban.
Malangnya, hampir dalam setiap kasus sengketa tanah, posisi masyarakat selalu lemah (atau “dilemahkan”). masyarakat sering tidak memiliki dokumen-dokumen legal yang bisa membuktikan kepemilikan tanahnya. Mereka bisanya hanya bersandar pada “kepemilikan historis”: tanah yang mereka miliki telah ditempati dan digarap secara turun-temurun.
Di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya termaktub satu ketentuan akan adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya (pasal 9 ayat 2). Jika mengacu pada ketentuan itu―dan juga merujuk pada PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah (terutama pasal 2)―Badan Pertanahan Nasional (BPN) semestinya dapat menerbitkan dokumen legal (sertifikat) yang dibutuhkan oleh setiap warga negara dengan mekanisme yang mudah; terlebih lagi jika warga negara yang bersangkutan sebelumnya telah memiliki bukti lama atas hak tanah mereka (petok, leter C, girik, kikitir, dls.).
Namun, sialnya, pembuktian dokumen legal melalui sertifikasi pun ternyata bukan solusi jitu dalam kasus sengketa tanah. Seringkali sebidang tanah bersertifikat lebih dari satu, pada kasus Meruya yang belakangan sedang mencuat, misalnya. Bahkan, pada beberapa kasus, sertifikat yang telah diterbitkan pun kemudian bisa dianggap aspro (asli tapi salah prosedur) seperti yang dialami oleh warga Desa Kertaharja dan Sindangsari Kecamatan Cimerak, Ciamis, yang pada tahun 1979 tanah mereka diserobot proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) yang dikelola PTP XIII.
••
BAGI para petani, tanah bukan hanya masalah ekonomi atau eksistensi. Lebih dari itu, tanah adalah soal (hak) hidup itu sendiri. Tatkala sudah menyangkut soal (hak) hidup, maka menjadi teramat wajar jika pilihannya hanya tinggal, bagaimana “hak itu harus terus dipertahankan dan diperjuangkan”.
Satu ilustrasi menarik yang barangkali bisa disimak dalam kaitannya dengan konstelasi masalah tanah (agraria) di Indonesia, misalnya saja, yang berkaitan dengan fenomena perubahan bentang alam, sebagaimana yang terjadi di Laguna Sagara Anakan, Cilacap. Akibat sedimentasi dan pendangkalan yang terus-menerus, sebagian besar areal Sagara Anakan kini sudah nyaris menjadi daratan: dipenuhi tanah timbul.
Tanah timbul itu kemudian mulai dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kampung Laut yang hidup di sekitar Sagara Anakan untuk menetap dan bertani. Masyarakat Kampung Laut sendiri adalah masyarakat nelayan. Masyarakat Kampung Laut harus kehilangan sebagian besar sumber nafkah seiring dengan laut yang menjadi sandaran hidup mereka semakin dangkal dan menyempit. Mereka beralih profesi bukan karena ingin menjadi petani, terlebih dengan kehendak untuk memiliki dan menguasai tanah timbul. Beralih profesi menjadi petani adalah cara yang dipandang paling logis (dan paling mungkin) untuk dilakukan agar mereka bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya.
Keberadaan masyarakat di tanah timbul itu pun bukannya tanpa sengketa. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam konteks tanah timbul itu. Selain masyarakat, paling tidak di sana ada LP Nusakambangan, Perhutani, dan Badan Pengelola Konservasi Sagara Anakan (BPKSA) yang lebih punya perhatian pada hutan mangrovenya. Masyarakat pun bukannya tanpa ada kesadaran dengan status tanah timbul itu sendiri. Justru, dalam kecemasannya, mereka senantiasa menginginkan kepastian jawaban atas pertanyaan sederhana: “Tanah timbul itu milik siapa? Bilakah mereka berhak nunut nandur di tanah timbul yang dulunya adalah laut tempat mereka menyandarkan hidup?”
Kecemasan masyarakat itu memang sangat beralasan. Sampai saat ini, status tanah timbul sepertinya memang masih belum diatur secara eksplisit dalam suatu aturan perundangan tertulis. Dengan melihat kondisi di lapangan, tidak akan menutup kemungkinan―dengan adanya berbagai pihak yang memiliki kepentingan―fenomena keberadaan tanah timbul di wilayah Sagara Anakan itu pun sesungguhnya tengah menebar bom waktu yang suatu saat bisa meledak jika tidak ada penanganan dan penyelesaian yang komprehensif, terutama dalam konteks kepastian hukumnya.
Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No.5/1960 tentang Pokok Agraria, UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keppres No.34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, pada dasarnya memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah-masalah agraria. Adalah sudah selayaknya―terlepas dari berbagai kekurangan yang tersimpan di dalam instrumen-instrumen hukum itu―jika kewenangan tersebut dimplementasikan, dengan prinsip-prinsip yang tidak melawan hukum itu sendiri tentunya.
Sementara itu, gagasan untuk membentuk kelembagaan dan mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa tanah―semacam Komisi Nasional Penyelesaian Sengketa Agraria dan juga pembentukan lembaga sejenis di daerah―sebagaimana yang pernah diusulkan oleh berbagai kalangan, kiranya menjadi relevan pula untuk semakin didesakkan; terlebih jika pemerintah memang benar-benar berkehendak untuk menjalankan reforma agraria dan menangani permasalahan agraria secara serius. Belajar dari tragedi Pasuruan, jika Badan Pertanahan Nasional mencatat ada 2.810 kasus sengketa tanah yang berskala nasional, maka boleh dibayangkan bagaimana hebatnya bom waktu yang akan meledak jika kasus-kasus tersebut tidak segera mendapatkan penanganan dan penyelesaian yang layak dan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sampai hari ini barangkali masih hanya sebatas retorika. Yang kerap terjadi justru sebaliknya: rakyat yang kehilangan kemakmuran sebesar-besarnya. Empat warga Desa Alas Tlogo Pasuruan, bukan hanya kehilangan kemakmuran. Lebih dari itu, mereka telah tercabut hidupnya.
Boleh jadi, mereka adalah martir, dan semoga saja mereka pun adalah korban yang terakhir.
²²²
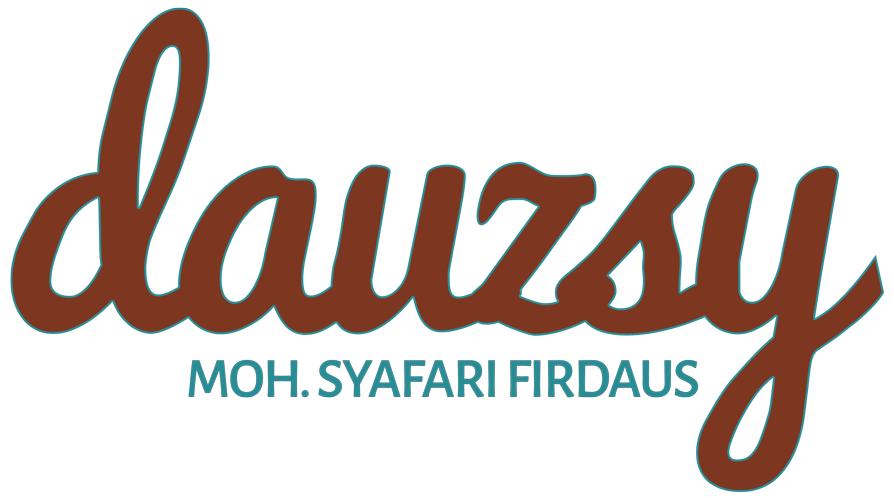

2 komentar
Rakyat selalu kalah. Negara hanya sebagai penjajah. Sudah waktunya rakyat berkuasa dan mengambil alih kekuasaan ini dengan caranya sendiri. REVOLUSIII !!!
Mari kita adakan revolusi.
“Dor!”
“If you want shot get shot don’t talk, if you talk I shot you!” begitu dalam suatu dialog film koboy amrik. Setelah menembak musuhnya yang menyempatkan bicara sewaktu secara tiba-tiba berhadapan.
Namun berbagai model budaya perubahan bukanlah keadilan abadi. Seperti juga revolusi dan evolusi yang sudah tergolong setiap hari terjadi dengan berbagai modifikasinya yang tidak kasad mata tapi terasa dengan berbagai rasa oleh rakyat. Apakah rakyat yang miskin, yang bersenjata, yang berkuasa, yang kaya, yang pinter atau yang bukan siapa-siapa.
Apa pun, bagi saya sungguh sulit untuk memilih menjadi meledak-ledak untuk mengerjakan sesuatu yang diharapkan bisa menjadi penerang menuju keadilan yang bahagia. Hati saya selalu berkata: Aku tidak bisa berkata bahwa aku bukan salah satu dari mereka…