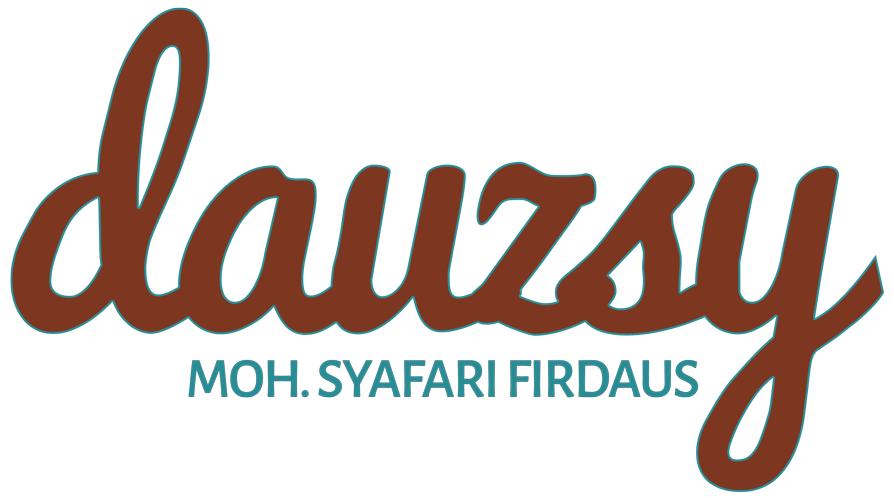Jika menengok kembali peta perjalanan dunia perfilman Indonesia, kita akan mendapatkan kenyataan bahwa film (layar lebar) Indonesia sempat mendapat tempat yang cukup layak di tengah-tengah masyarakatnya. Era 1970-an hingga paruh 1980-an boleh dicatat sebagai masa keemasannya. Sumandjaja, Arifin C. Noer, Wim Umboh, atau Teguh Karya, merupakan sejumlah sineas yang cukup gemilang dalam menghasilkan karya-karya kreatifnya. Masyarakat pendukungnya pun, terutama dalam hal ini publik penontonnya, terhitung masih sangat potensial dan cukup apresiatif.
Kondisi yang cukup kondusif seperti itu memang boleh dimungkinkan karena publik pada saat itu barangkali relatif tidak banyak memiliki alternatif lain untuk memilih bahan tontonan sebagai hiburannya. Stagnasi dunia film Indonesia mulai tampak ketika film-film impor sudah semakin mudah masuk ke wilayah pasar Indonesia. Peta perfilman Indonesia pun mulai menampakkan pergeseran. Persaingan antara produksi film Indonesia dengan film impor yang pada awanya sempat terjadi begitu ketat, akhirnya tidak lagi bisa berjalan secara seimbang: film Indonesia mulai harus merelakan dirinya untuk tersisihkan dari publik penontonnya sendiri. Film-film impor, terutama produksi Hollywood, yang keberadaannnya lebih beragam, tampaknya lebih bisa dinikmati oleh publik penonton kita tinimbang film-film Indonesia yang memang cenderung monoton. Produksi mereka pun mampu dikemas dengan sangat baik dan menarik. Lebih dari itu, produksi film mereka pun lebih didukung oleh perangkat teknologi.
Bagaimanapun, haruslah diakui jika film memang merupakan genre seni yang harus terlahir sebagai anak dari teknologi. Dimensi audio-visual yang dimiliki oleh film, telah memberi peluang dan ruang gerak yang lebih leluasa bagi perkembangan teknologi untuk bisa semakin memanjakan dan menghibur penontonnya. Tampaknya, pemanjaan dan penghiburan semacam inilah yang lebih diminati oleh sebagian besar publik penonton kita. Sementara film-film Indonesia masih belum cukup sanggup untuk memfasilitasinya.
Selain faktor kemasan dan teknologi tadi, dunia perfilman kita pun agaknya tidak begitu didukung pula oleh sistem produksi dan manajemen industri (distribusi dan promosi) yang kokoh. Dalam hal ini, pola yang dibangunnya terkadang “absurd”. Syahdan, sering terbetrik cerita bahwa produser bisa begitu berkuasa dalam menentukan segalanya. Kreativitas yang ditunjukkan seorang sutradara cukup hanya sebatas manut saja. Demikian pula halnya dengan para aktornya yang kerapkali harus berdalih, “Begitulah tuntutan skenario!”
Sementara itu, sebagai bagian yang sudah tidak terpisahkan dari industri khas kapitalis, memang merupakan suatu hal yang sangat wajar dan realistis jika dalam sebuah produksi film harus memperhitungkan segmen pasarnya. Namun, hal ini bukan lantas berarti “pasar” adalah segalanya. Relasi dengan “pasar” ini pun tentu saja harus tetap diimbangi dengan kualitas dari produk yang ditawarkan.
Hal ini pula yang kerap terabaikan oleh sebagian besar para pelaku perfilman di Indonesia. Dengan menganggap “pasar” adalah segalanya, mereka hanya melihat apa yang dikehendaki “pasar” tanpa terlalu jauh memikirkan mutu produknya, terlebih sampai pada taraf adanya usaha untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang mungkin bisa menggiring, melatih, hingga pada akhirnya bisa membentuk segmen pasarnya sendiri. Maka tidaklah terlalu mengherankan jika banyak kalangan yang menilai, sebagian besar produk film-film Indonesia cenderung hanya begitu-begitu saja, seragam, dan membosankan: daging tidak ikan pun bukan.
Sebagai konsekuensi logis yang kemudian harus diterima, lambat laun “pasar” justru melakukan penolakan, terlebih ketika produk film Indonesia itu dapat dengan mudah mereka bandingkan dengan produk film-film impor yang lebih menyegarkan. Dan tragisnya, dampak yang sama sekali tidak menguntungkan ini harus terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan kini, bukan hanya publik penontonnya saja yang telah meninggalkan film Indonesia, tapi juga dengan sebagian besar sineasnya yang telah berbondong-bondong menempuh hidup baru di jalur persinetronan yang tampaknya dianggap lebih nyaman dan menguntungkan dalam segala hal.
* *
Demikianlah, kondisi dunia perfilman kita itu pun hingga kini masih harus terbaring parah. Sakit berkepanjangan yang dideritanya, tampaknya masih belum juga menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan: hidup enggan, mati pun tak kunjung tiba. Nasibnya sungguh mengenaskan. Sekian lama ia hanya bisa mengap-mengap tak berdaya dan tampak begitu menderita. Betapa ia yang dulunya sempat berjaya, kini harus merelakan dirinya untuk terenggut dari dunianya, justru ketika arus budaya tontonan tengah sedemikian pesat merambah wacana keseharian kita. Ironis memang, namun apa mau dikata.
Selama ini, memang telah ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh sementara kalangan yang masih menaruh kepercayaan bahwa dunia perfilman Indonesia akan bisa kembali tegar mengibarkan bendera eksistensinya. Di antara para sineas kita, nama Garin Nugroho boleh dicatat sebagai salah satu dari segelintir yang masih bertahan untuk berjalan di rel ini. Ia tetap konsisten untuk menghasilkan karya-karya (film) kreatif, meski tetap saja menjadi ironis ketika karya-karyanya itu, lewat sejumlah festival yang diikutinya, justru lebih dikenal dan dihargai di dunia internasional tinimbang di negerinya sendiri. Terakhir, mungkin hanya film Daun di Atas Bantal (1997, beredar tahun 1998) yang sempat ditonton oleh publik kita secara luas. Entah pula bagaimana nasibnya dengan film Puisi Tak Terkuburkan, sebuah film yang konon berbicara ihwal Aceh, yang rencananya akan beredar pada bulan Maret 2000 ini.
Selain dari kalangan sineas, ada pula beberapa lembaga yang tampaknya masih cukup peduli untuk mengurusi keterpurukan dunia perfilman kita. Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia, misalnya, yang pada bulan November 1999 lalu menggelar ajang Jakarta International Film Festival (JIFFest). Ajang JIFFest yang pertama ini patut dicatat sebagai sebuah usaha yang cukup penting, terutama untuk mulai menggairahkan kembali kehidupan perfilman Indonesia dari keterpurukannya. Bagi kalangan perfilman kita sendiri, selain bisa dimanfaatkan sebagai ajang komparasi yang lebih komprehensif (tidak hanya dengan film-film produksi Hollywood atau Mandarin yang selama ini praktis menguasai pangsa pasar kita), di sini sangat terbuka pula peluang untuk memberi pengayaan, baik di tingkat wacana maupun di sisi ruang kreativitasnya.
Begitu pula halnya dengan upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (Senakki). Pada tahun 1994, misalnya, lembaga ini pernah melakukan suatu upaya untuk mengedarkan film-film yang dianggap berkualitas, di antaranya adalah film Surat Untuk Bidadari (Garin Nugroho, 1993) dan Badut-Badut Kota (Ucik Supra, 1994), dengan cara “mengamenkan”-nya ke sejumlah kampus. Usaha ini ditempuh karena film-film tersebut tidak bisa dinikmati publik akibat tidak adanya distributor yang berkenan untuk memasarkannya ke bioskop-bioskop karena, dalam hitungan ekonomis, dianggap tidak akan menguntungkan.
Pada tanggal 26 Ferbuari 2000 yang baru lalu pun Senakki telah menggelar Festival Film Kine Klub (FFKK) yang menganugrahkan Kine Award kepada para pelaku perfilman Indonesia. Festival yang rencananya akan dilangsungkan setiap 2 tahun sekali tersebut, harapannya boleh jadi akan bisa sedikit memberi angin segar dan percikan gairah baru pula bagi denyut kehidupan dunia perfilman kita, setelah keberadaan Festival Film Indonesia (FFI)—yang sempat menjadi ajang kompetisi yang cukup prestisius dan bergengsi bagi dunia perfilman Indonesia—menghilang dari peredarannya.
Akan tetapi, hadirnya ajang festival semacam ini tentu bukan merupakan jaminan, dunia perfilman kita itu sedikit demi sedikit akan bisa terdongkrak sebagaimana yang diharapkan. Boleh jadi malah akan terjadi sebaliknya; ajang festival ini akan kembali berakhir seperti halnya FFI atau FSI (Festival Sinetron Indonesia) yang kerap tersendat-sendat, atau lebih dari itu bahkan dianggap kurang representatif dalam hal penilaian dan legitimasinya; tidak seperti Academy Award, misalnya, yang nyaris selalu dipandang legitimatif dan jaminan mutu.
Hanya saja, yang patut dicatat dari itu semua, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh segelintir kalangan yang masih peduli terhadap dunia perfilman kita itu, mudah-mudahan tidaklah menjadi sia-sia. Paling tidak, hal itu mungkin akan bisa memberi sekadar tambahan nafas yang sejenak akan meringankan sesak yang diderita oleh dunai perfilman kita, meski itu pun kiranya hanya merupakan obat sesaat yang sama sekali masih jauh dari harapan untuk bisa menyembuhkan. Selebihnya, dunia perfilman Indonesia masih harus berjuang keras melawan segala penyakit yang telah begitu lama mengendap pada dirinya. Kalaupun dunia perfilman kita itu masih diharapkan untuk bisa tetap hidup, tampaknya masih akan sangat dibutuhkan kesabaran ekstra dan kekerasan kepala dari semua pihak yang turut terlibat di dalamnya.
* * *