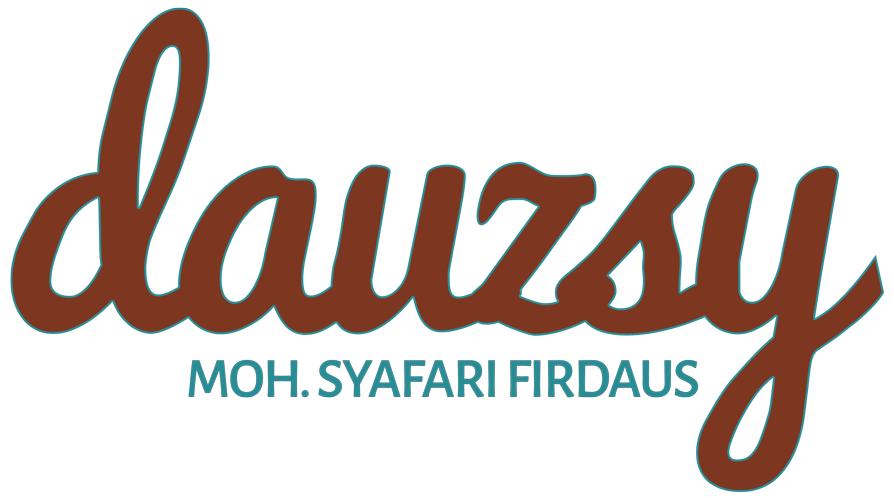TENTU saja Kades Bagja amat sangat terkesiap ketika di siang yang sungguh cerah ceria itu, Hansip Didi dan Hansip Herman datang tergopoh-gopoh menemuinya, dan melaporkan bahwa serombongan warga desa kini tengah beramai-ramai dalam perjalanan menuju kantor desa. Di tengah kegugupannya, Sekdes Amin malah sudah mengambil inisiatif untuk segera membereskan segala sesuatu yang sekiranya bisa ia bereskan: menyelamatkan aset desa. Wajahnya yang cekung itu tampak menegang. Dengan suara gemetar tertahan-tahan, beberapa kali terdengar ia berkata: “Celaka, Pak! Celaka!”
“Apa kalian tidak salah lihat?” Kades Bagja minta lebih diyakinkan.
“Waduh, Pak. Sungguh. Ini serius!” ucap Hansip Herman.
“Positif. Asli. Bukan basa-basi!” timpal Hansip Didi.
“Mereka tak bisa dicegah.”
“Merambah seperti air bah.”
“Parang, pacul, linggis, arit—”
“Semprotan hama pun mereka bawa, Pak!”
“Spanduknya pun besar-besar! Isinya—”
“Celaka! Ini jelas-jelas celaka!” kembali terdengar Sekdes Amin berkata di tengah kegugupannya. Wajahnya semakin tegang saja. Beberapa kali pula ia harus mengelap wajahnya yang tiba-tiba kebanjiran keringat dingin itu. Huhh! Bagaimanapun, ia lihat sendiri di TV—
Maka seterusnya mulutnya itu pun kini tak henti berkomat-kamit.
“Mereka itu katanya mau apa?” tanya Kades Bagja yang tampak masih juga belum mau percaya.
“Lho, Bapak ini gimana, tho. Terang mereka mo demo, dong.”
“Demo?”
“Seperti di TV.”
“Lha wong itu yang lagi musim. Trendi.”
“Tiada hari tanpa aksi dan demonstrasi.”
“Husshy!”
“Mesti ada dalang intelektuil di belakang ini semua!” sela Sekdes Amin yang kini sudah semakin kerap mengelap keringat di wajahnya. Sebentar-sebentar ia berdiri, berjalan hilir mudik, lalu duduk lagi. “Pasti!”
Kades Bagja tampak masih mencoba untuk tetap tenang sekalipun hatinya sendiri tak urung dag-dug juga. Seperti juga Sekdes Amin, ia pun melihat sendiri bagaimana di TV—
“Jadi sekarang apa yang mesti kita lakukan, Pak?” tanya Hansip Herman.
“Lapor polisi?” usul Hansip Didi.
Kades Bagja menarik nafas dalam. Sejenak ia tampak termenung. Dalam kepalanya kini berkecamuk setumpuk pikiran dan pertanyaan perihal warganya itu. Ada apa? Ia sendiri sungguh belum mau percaya jika warganya yang kini tengah beramai-ramai dalam perjalanan menuju Kantor Desa berniat akan berdemonstrasi sebagaimana kabar yang dihembuskan oleh kedua aparatnya ini.
Lalu kenapa? Apa yang terjadi? Bilakah warganya itu telah termakan isu? Provokasi? Kepiting rebus! Gerangan siapakah yang telah berani-beraninya menyebar isu dan provokasi di wilayah kekuasaannya ini? Isu perihal apa? Provokasi macam mana? Politik? Ekonomi? Sosial? Budaya? Hankam? HAM? SARA? Atau, aduh, jangan-jangan ini adalah sebentuk ekses gara-gara kemarin ia membonceng pulang Ibu Guru Desy. Bermotifkan jealousy? Mereka ditunggangi oleh orang yang cemburu! Isunya itu mungkin berbunyi: “Ada asmara di balik motor baru Kades Bagja: skandal jeprut!”
Wehh, gawat juga itu. Tapi, ah, masa iya? Bukanlah segenap warganya itu ia kenal sebagai masyarakat yang berbudi, arif-bijaksana, dan lebih dari itu, sangat kritis pula? Alangkah sungguh mengherankan jikalau kini mereka bisa dengan begitu mudah tersulut provokasi, terlebih hanya karena isu dan gosip murahan macam itu. No way! Mereka tak berketombe. Tak ada dalam kamusnya kalau mereka sampai mau melakukan tindakan anarkis dan inkonstitusional yang sangat potensial untuk menghancurkan konformitas, tatanan harmonis yang selama ini mereka jaga bersama-sama. Ya, singkat kata, ia masih sungguh sangat percaya dengan kedewasaan berpikir dan bertindak dari segenap warganya.
“Jadi, bagaimana sekarang, Pak?” desak Hansip Herman.
“Tak ada waktu lagi. Pilihannya hanya tinggal mengungsi atau lapor polisi!” tandas Hansip Didi.
Kades Bagja kembali hanya tepekur di kusinya. Keningnya tampak berkerut. Alis matanya yang bak rumput bergoyang itu, tampak turun-naik. Di hadapannya, kedua aparatnya berdiri khidmat memperhatikan, siap menunggu putusannya. Hanya Sekdes Amin saja yang tetap sibuk sendiri bergelut dengan keringat yang tak juga jera mengerubuti wajahnya. Sesekali matanya melongok ke luar jendela, larak-lirik ke arah tikungan jalan.
••
MASIH belum terlihat tanda-tanda Kades Bagja berkenan untuk angkat bicara. Bukannya ia tidak mengindahkan kekhawatiran sebagaimana yang diutarakan oleh kedua aparatnya itu. Kepenasarannya untuk menemukan benang merah di balik peristiwa yang sebentar mungkin akan terjadi, masih terlalu perkasa menggerayangi hasratnya sebagai Kades yang telah tiga kali memegang tampuk perintah. Ya, situasi macam apa yang tengah dihadapinya? Bermuara pada dirinyakah persoalan yang kini dibawa mereka?
Betul, bahwa sepanjang karirnya sebagai kades, sampai saat ini ia memang sama sekali belum pernah terpilih menjadi Kades Teladan sebagaimana yang di setiap tahunnya selalu diadakan pihak kecamatan, guna diwakilkan untuk memperebutkan predikat serupa di tingkat kabupaten, dan begitu seterusnya. Tapi hal itu kiranya bukanlah persoalan esensial. Ya, boleh jadi memang signifikan. Namun, segenap warganya (c.q. Dewan dan Sidang Paripurna Musyawarah Desa) selama ini tidak pernah menganggapnya sebagai agenda penting yang pantas untuk dipericuhkan. Lagi pula, sangatlah bisa dimengerti, dan bukankah seluruh warganya itu pun mengetahui, ketidakpernahannya terpilih menjadi Kades Teladan adalah semata-mata karena, secara de facto, ia memang tidak pernah dilibatkan untuk dinilai dalam pemilihan itu?
Ia masih ingat betul ketika sekali waktu Pak Camat berkenan mengunjunginya. Setelah ngobrol ngalor-ngidul ini-itu plus sedikit mengupas gosip dan berdiskusi ihwal konstelasi perpolitikan yang tengah semarak, sampailah juga Beliau pada pembicaraan yang berkenaan dengan acara tahunan pemilihan Kades Teladan yang dalam beberapa bulan di depan akan dilaksanakan. Pada intinya, Pak Camat yang baik hati itu ingin memberitahukan bahwasannya, setelah berkonsultasi dengan pihak kabupaten, dalam pemilihan Kades Teladan nanti, meskipun keberadaan dirinya sebagai seorang Kades yang sah tidak kehilangan hak untuk turut berlaga dan akan tetap dicatat sebagai salah seorang kontenstan, namun di dalam proses penilaiannya ia tidak akan turut dikompetisikan dengan kades-kades yang lain. Alasannya, sebagaimana yang seterusnya dibeberkan dengan sangat panjang lebar, dengan melihat realitas yang berkembang di desa yang dipimpinnya ini—atau yang dalam bahasanya Pak Camat itu, “keberhasilan untuk membangun manusia seutuhnya”—maka secara objektif harus diakui bahwa tidak akan pernah ada kandidat kades lain yang akan bisa menandinginya untuk menyabet predikat Kades Teladan: praktis tak akan ada saingan.
Dalam pandangan Pak Camat, dan juga konon dalam pandangan para pembesar di kabupaten, kondisi seperti itu justru tidak kondusif: tidak baik bagi pembelajaran. Kades-kades yang lain mungkin saja akan minder atau bahkan patah arang sebelum berperang ketika mereka melihat kenyataan bahwa sangat pasti mereka akan kalah di segala lini kalau sampai harus menghadapinya. Dengan begitu, jalannya proses pemilihan jelas tidak akan seru: tidak akan memupuk jiwa kompetitif mereka untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Lagi pula, seiring dengan tujuannya yang dimaksudkan agar Kades Teladan pada akhirnya diharapkan akan bisa menjadi teladan bagi seluruh jajaran kades, kalaupun ia yang sampai harus menjadi Kades Teladan, dengan segala keberhasilan yang telah dicapainya, maka akan sangat sulit bagi kades-kades lain untuk bisa mengikuti keteladanannya itu. Maka dari itu, untuk menyelamatkan kemuliaan maksud dan tujuan tadi, ia diminta kesediaannya untuk rela berkorban demi serunya acara pemilihan nanti.
“Ya, semoga saja Dimas Bagja bisa mengerti dengan segalanya,” demikian ucap Pak Camat menutup semua penjelasannya. Sedangkan ia sendiri sedari pertama hanya manggut-manggut mendengarkannya.
Kalaupun boleh berbangga, predikat Kades Teladan tidaklah akan bernilai apa-apa bagi dirinya, dan begitu pula bagi segenap warganya. Ada setumpuk cerita sukses yang lebih menghebohkan lagi perihal desanya ini. Akan terlalu panjang kalaulah itu harus diceritakan.
Namun halnya sekarang, gerangan apakah yang menjadi biang permasalahannya? Soal Kades Teladan itu, nyaris bisa dipastikan, bukan! Hm, mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan dirinya? Dengan kepemimpinannya? Bilakah ia telah melakukan tindakan fatal tak termaafkan yang mengakibatkan warganya kini harus uring-uringan?
Ya, tapi bagaimana bisa? Menurut pikiran dan perasaannya, sekian banyak yang telah ia lakukan nyaris tak ada yang mengecewakan. Sepanjang yang berkenaan dengan kepentingan desanya, sejauh yang ia ingat, seluruh agenda kerja yang diproyeksikannya sudah ia konsultasikan terlebih dulu dengan segenap anggota Dewan Desa dan sudah di-ACC pula dengan gilang-gemilang oleh Sidang Paripurna Musyawarah Desa. Begitu pun halnya dengan segala produk kebijakan yang kemudian dimaklumatkan, terlebih dulu akan selalu melalui prosedur seperti itu: selalu transparan.
Singkat kata, everything is great! Sungguh. Sebagai timbal balik atas respektivitas, penghargaan, dan kepercayaan yang telah ia abdikan sepenuhnya untuk kepentingan desa dan warganya, maka demikianlah pula dengan kepemimpinannya yang dilegitimasi dengan sepenuh hati oleh mereka. Laras. Iklim kondusif. Roda demokrasi berputar mulus. Nyaris sempurna. Dengan kondisi seperti itu pula yang telah membawa dan mewujudkan perikehidupan desanya ini menjadi sebuah masyarakat yang adil-makmur gemar-ripah loh jinawi repeh-rapih toto-tengtrem kerto raharjo, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Di desanya ini, memayu hayuning buana, bukan lagi sekadar manisnya retorika.
Ini betul, lho! Nyata. Bukan cuma sekadar rahul kalau ia harus bilang begitu. Bahkan, penilaian semacam ini diberikan pula oleh para sosiolog dan antropolog yang dulu sempat tertarik untuk mengadakan penelitian di desanya ini. Terus terang saja, kalau Anda sendiri sukar untuk percaya dengan apa yang disebut tadi, memang sangat wajar. Pada awalnya, para sosiolog dan antropolog yang melakukan penelitian cukup lama itu pun nyaris tidak habis pikir dengan keadaan yang mereka temukan di lapangan. Bagi mereka, apa yang ditemukan di desanya ini merupakan sebuah fenomena yang sungguh menakjubkan. Mereka sendiri menyebutnya sebagai desa utopis yang bukan sekadar utopia. Jika tidak menyimak dan mengalaminya secara langsung, mereka mengaku akan sangat sukar untuk bisa percaya dan menerima kenyataan bahwa benar-benar ada realitas sosial yang nyaris ideal semacam ini. Seperti juga yang diakui mereka, selain merupakan bahan penelitian yang menarik, pada tahap tertentu kenyataan ini pun telah memaksa mereka untuk kembali memeriksa—atau bahkan harus merevisi—nyaris semua teori akademis yang telah mereka pelajari.
Akan tetapi, apakah semua itu kini harus lenyap ditelan sebuah peristiwa yang sebentar mungkin akan terjadi? Akan berakhir tragiskah konformitas nan harmonis desanya ini? Ditutup lara dan malapetaka? Sungguh, kalaupun itu benar-benar terjadi—
Dan sekali lagi, hanya sebentuk desah nafas panjangnya itu saja yang menutup segala pertanyaan yang kian hibuk berkecamuk di kepalanya.
“Jadi bagaimana, Pak?” Hansip Herman kembali minta kepastian.
“Mesti taktis, Pak. Segera!” Hansip Didi menambahkan. “Waktu kita semakin sempit! Kalau tidak—”
“Terlambat!” pekik Sekdes Amin yang sedari tadi terus berdiri di tepian jendela. “Mereka sudah datang!”
Hansip Herman dan Hansip Didi gegas beranjak mendekati Sekdes Amin. Dari balik kaca jendela itu, jelas terlihat bagaimana berbondong-bondongnya warga yang memenuhi jalan protokol desa tengah berjalan cepat menuju ke arah mereka. Suara riuhnya itu pun sudah mulai sayup semilir terdengar; lapat-lapat, dan sebentar kemudian semakin dekat, semakin tegas— Dan tak berapa lama kemudian teriakan demi teriakan itu pun mulai bergolak, menguncang-guncang pelataran kantor desa yang luasnya tak seberapa:
“Keluar, Kades Bagja!”
“Menyerahlah! Kantor ini sudah kami kuasai.”
“Kalian sudah terkepuuuung!”
Pletar! Pletar! Beberapa kali terdengar pula suara ledakan. Susul-menyusul.
“Hadapi kami di sini!”
“Sekali-kali you musti lihat kita punya kelakuan, Bagja!”
“Keluar, Bagja!”
“Keluaarrr!!”
Ruang kantor desa yang berisikan empat orang itu untuk beberapa saat tinggal dicekam sunyi. Hansip Herman, Hansip Didi, dan Sekdes Amin hanya saling pandang satu sama lain. Tegang menyucuk. Sementara teriakan demi teriakan dari luar kian menjadi: keributan alang kepalang yang boleh dicatat sebagai yang pertama terjadi di desa ini.
“Lu takut, Bagja!”
“Kita punya urusan besar!”
Kades Bagja pelan berdiri dari kursinya seraya mengelap keringat yang tak terasa telah mengucur pula dari keningnya. Sejenak ditatapnya ketiga aparatnya itu. Huhh! Meskipun dengan hati gundah, namun kini ia tampaknya harus memilih untuk bersiap pasrah dengan segala keadaan yang mungkin akan ia terima. Setapak ia melangkah ke muka, untuk seterusnya tegap mendekati pintu dan membukanya.
Begitu pintu terbuka, Kades Bagja langsung disambut dengan suara-suara ledakan dan gemuruhnya teriakan demi teriakan. Meski mencoba untuk abai, tak urung hatinya tetap gemertuk. Di ambang pintu itu, sesaat ia berdiri, melemparkan pandangannya ke seluruh penjuru. Seperti yang telah diceritakan oleh kedua aparatnya tadi, kini ia bisa menyaksikan sendiri bagaimana keberingasan yang ditunjukkan warga desanya ini. Huhh! Bahkan para anggota Dewan Desa yang biasanya selalu berpembawaan kalem dan penuh perhitungan itu pun kini dengan begitu bersemangatnya turut mengacung-acungkan kepalan tangan dan melambai-lambaikan sepasang spanduk panjang yang masing-masing bertuliskan: “Beri kami kesempatan! Jangan harap lolos dengan selamat!”
Setelah menarik nafas panjang untuk kesekian kalinya, dengan langkah ragu-ragu Kades Bagja lantas berjalan ke arah teras depan. Sebisa-bisanya ia pun kemudian mencoba untuk menenangkan. Sia-sia. Hanya suara gemuruh, “huuuuuu!” yang ia terima sebagai tanggapan dari mereka. Tak ada lagi yang kiranya berkenan untuk mendengarkan.
••
PRANG-PRING sabulu-bulu gading. Keriuhan telah kian menjadi. Naga-naganya akan bertambah runyam. Di sana, Kades Bagja sendiri kini hanya tinggal bisa menelan ludahnya. Lututnya pun sudah tampak agak goyah. Keringat di keningnya semakin deras mengucur. Belum lagi dengan sengatan matahari yang dirasa begitu tepat mengarah ke wajahnya.
“Sudah, kita serbu saja sekarang!” pekik seseorang.
“Ya, kita kasih dia pelajaran!” sambung yang lainnya.
“Habisi! Biar nyaho!”
“Majuuuu!”
Tanpa dikomando lebih lanjut, serempak mereka maju ke muka. Kades Bagja terhenyak. Rasa kecut dan miris itu kian menjalarinya. Ingin sekali ia undur dari tempat berdirinya, cabut dari situ, hambur menyelamatkan diri. Namun apa daya, lututnya yang sudah semakin goyah itu hanya mampu gemetaran. Yang kemudian ia lakukan cuma menguat-nguatkan dirinya dengan memejamkan mata. Pasrah. Dalam bayangannya, tiada lain, mati! Maka, diam-diam Kades Bagja pun bersumpah akan menjadi arwah gentayangan karena harus mati sebagai kades yang penasaran.
Di tengah gemertuk dan debar hatinya, Kades Bagja menunggu apa yang akan menimpanya. Sesaat lewat, belum terjadi apa-apa. Sekian lama kemudian, masih belum juga terasa apa-apa. Begitupun seterusnya. Bahkan keriuhan warganya itu kini malah susut tiba-tiba. Ia tak lagi mendengar setetespun suara atau derap langkah kaki mereka. Sepi. Hatinya pun lantas menerka-nerka, sudahkah kini ia berada di surga?
Dengan sangat perlahan Kades Bagja memberanikan diri untuk membuka matanya. Sekejapan ia hanya terpaku, sebelum kemudian disapukan pandangan matanya itu. Ya, sejauh ini tampaknya memang masih belum terjadi apa-apa. Ia masih berdiri di sana. Juga masih dilihatnya segenap warga desanya itu yang kini berderet-deret mengelilinginya, dan tengah menujukan segenap perhatian ke arahnya. Masih tak ada suara. Sementara Kades Bagja sendiri kini tinggal kebagian melongo culun untuk balas menatap mereka.
Belum juga ia sempat sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi, segenap warga desanya itu dengan serempak rame-rame berteriak: “Selamat ulang tahuuuun!”
“Surpriiiise!” dan potongan kertas warna-warni itu pun dengan semarak mereka hamburkan ke udara. Melayang-layang. Berkerlap-kerlip. Lagu Selamat Ulang Tahun dan Happy Birthday pun segera menggema di sana, diiringi luapan tepuk riuh yang menggelora. Tak ketinggalan pula suara terompet dan petasan: tot-tet! tot-tet! pletar! pletar!
Maka, gonjang-ganjing di pelataran halaman kantor desa itu kini sontak berubah menjadi keramaian yang penuh senyum dan tawa. Mereka yang tadi berwajah beringas, seketika itu pula berganti menjadi sedemikian riangnya. Satu per satu mereka kemudian maju, bergantian menyalami Kades Bagja untuk mengucapkan selamat kepadanya. Tidak terkecuali dengan Sekdes Amin, Hansip Didi, dan Hansip Herman; ketiganya pun lantas bergantian menyalaminya.
Ya, sementara di tengah keriangan itu, di teras depan kantor desa, Kades Bagja sendiri kini lagi-lagi hanya mampu termangu. Gendok? Dongkol? Mangkel? Ah, tentu saja.
•••
Bandung, Pajajaran, 98/99/00