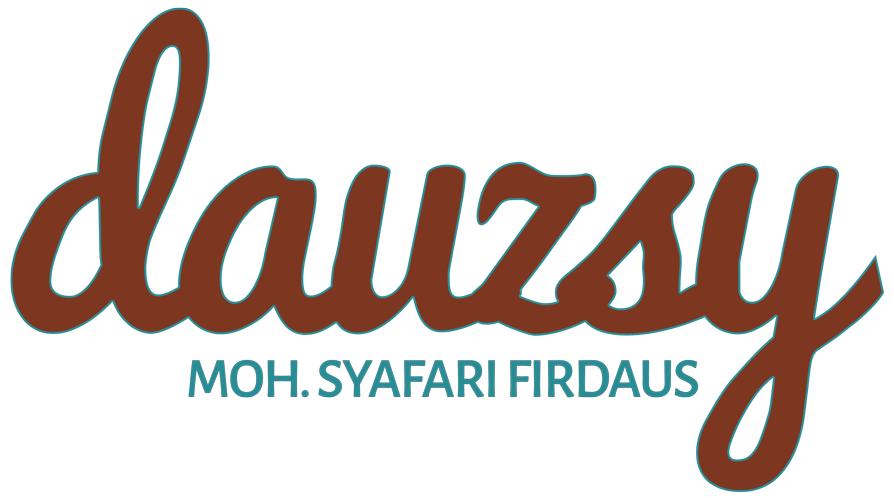Mempertanyakan, apakah sastra kita (masih) teralienasi, hingga saat ini memang boleh jadi tetap menarik untuk dikedepankan. Betul, ini lagu lama. Namun, senandungnya itu akan terus saja menggelitik selama keberadaan (kesu)sastra(an) kita masih menyisakan sederet persoalan yang pelik dan problematik. Lagi pula, masalah alienasi sastra ini tidak bisa ditarik hanya secara sinkronis, namun harus melihat pula aspek diakronisnya. Dengan kata lain, dari waktu ke waktu selalu akan membutuhkan adanya komparasi.
Menyoal alienasi sastra pada dasarnya menuntut kita untuk bersiap masuk dan berhadapan dengan sebuah wilayah narasi yang begitu kompleks. Masalahnya tidak akan bisa cukup terjelaskan jika kita hanya mencermatinya dari satu sisi dengan memilah, misalnya, fenomena yang tersimpan di dalam diri sastrawan (kreator), eksistensi sastra itu sendiri, dan masyarakat sosialisasinya. Tanpa mencoba untuk melibatkan dan membedah dialektika yang muncul dari adanya polarisasi tersebut, masalah alienasi sastra ini agaknya akan tetap dipandang dengan cara yang cenderung sepihak.
Halnya dengan alienasi sastra sebagaimana yang kemudian dipaparkan oleh Ahda Imran (PR, 2/8/1998) dari hasil pertautannya di Pertemuan Penyair Jawa Barat pada akhir Juli 1998. Kendatipun benar, seperti yang tersirat dalam tulisannya itu, bahwa kita tampaknya bisa menyimpan rasa optimis dengan melihat perkembangan sastra kita pada tahun-tahun belakangan, terlebih sebelum “rezim krismon” berkuasa, yang nafasnya kian menggelegak dan merambah untuk bersentuhan dengan banyak pihak, namun saya tidak akan buru-buru bersepakat dengan apa yang dikemukakannya. Bahwa, dengan menyimak gejala yang berkembang di Tasikmalaya dan Serang itu, misalnya, yang setidaknya telah mengisyaratkan jika sastra, puisi khususnya, sudah (boleh dipandang) bukan lagi milik dari “kelas-kelas tertentu” yang eksklusif, maka kita pun dengan serta merta bisa pula menepiskan pandangan akan adanya alienasi sastra?
Terus terang, saya sendiri masih meragukannya. Gejala yang dikedepankan oleh Ahda, kalaupun kemudian saya menggunakan term produsen-produk-konsumen, baru berpijak di wilayah produsen, belum mengurut jejak di wilayah produk dan konsumennya. Saya boleh yakin, jika alienasi sastra hanya dipandang di wilayah produsen semata, perbincangan berkepanjangan mengenai masalah ini tidak akan pernah mencuat ke permukaan; karena, bagaimana mungkin kita akan bisa mengidentifikasi adanya alienasi jika dari seluruh penduduk Indonesia, disadari ataupun tidak, sebenarnya sungguh ada banyak yang memproduksi teks-teks sastra? Contoh paling sederhana adalah fenomena para ABG yang gandrung bercinta dengan buku harian, misalnya. Akan tetapi, dari begitu banyak jumlah yang memproduksi teks-teks sastra, seberapa besar jumlah mereka yang bisa dikatakan benar-benar “dekat” dengan sastra? Di sini letak persoalan sebenarnya, karena alienasi sastra kaitan terpentingnya adalah justru dengan bagaimana “kedudukan produk” (teks-teks sastra itu) di wilayah society yang mengonsumsinya.
Hanya memang tidak bisa dipungkiri, “proses produksi” di wilayah produsen sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh komunitas Sanggar Sastra Tasikmalaya dan LiST Serang itu, misalnya, berperan cukup penting paling-tidak untuk memperpendek jarak distribusi antara produsen-produk-konsumen. Selain itu, upaya tersebut sedikit demi sedikit akan bisa menggerogoti dinding eksklusivitas sastra yang sementara ini memang dianggap sebagai salah satu biang keladi adanya alienasi. Demikian pula halnya dengan semangat dan intensitas produksi yang relatif akan bisa lebih terjaga tinimbang mereka yang memproduksi teks-teks sastra hanya sekadar memaksudkannya untuk “kekenesan” (atau keisengan), dengan kemungkinan mereka tidak berusaha untuk bersentuhan dan mengenali produk-produk sejenis, atau bahkan mereka sama sekali akan segera melupakan produk yang telah dihasilkannya itu.
Demikianlah, Ahda kemudian melihat proses produksi tersebut sebagai “sastra yang telah mengubah dirinya sebagai kata kerja”. Boleh jadi memang tidaklah terlalu berlebihan. Hanya saja, dalam konteks alienasi sebagaimana yang tengah kita bincangkan ini, hal itu agaknya masih membutuhkan deskripsi lebih lanjut (terlebih untuk sampai pada kesimpulan, ia memiliki kekuatan tawar dengan suatu mobilitas sosiologis yang seterusnya mampu mengendurkan cengkraman alienasi), yang tidak hanya cukup dengan menyebut, menulis puisi adalah kerja yang sekonyong-konyong diperlukan untuk katarsis; namun lebih pada proses bagaimana sastra yang telah menjadi “kata kerja” itu mampu meniscayakan dirinya untuk mendobrak alienasi.
Pada konteks ini akan tetap terselip persoalan tatkala disadari, kata kerja semacam ini tidak hadir dengan sendirinya dan tidak pula berdiri sendiri; ia berada dalam sebuah grand narasi, paling tidak yang membuat dirinya “ada” dan bisa dikenali. Di sini kita bisa menarik analogi, kata kerja tersebut pada akhirnya akan tersimpan di dalam sebuah kalimat; yang dengan begitu, ia dituntut untuk bersentuhan dengan seperangkat kelas kata lain yang membentuk kalimat tersebut. Belum lagi kalau harus menelusuri jejak jika kalimat itu berada dalam sebuah paragraf, sementara paragraf itu pun menyusun sebuah wacana. Tanpa melibatkan kaitan relasi ini, posisi kata kerja itu tidak lebih hanya akan menjadi sebentuk kekenesan juga; melepaskannya dari konteks yang membuat dirinya “ada”, pilihannya hanyalah tinggal menjadi sebuah kalimat imperatif yang sifatnya instruktif atau bahkan tidak berpijak sama sekali untuk kemudian tidak dikenali lagi. Jika ini pilihannya, maka ia sebenarnya justru telah mengalienasikan dirinya sendiri.
Dengan kata lain saya ingin menyatakan, setelah sastra bermetamorfosis menjadi kata kerja, yang menunggu di depan adalah tuntutan untuk mengenali keberadaan kata kerja itu di tengah realitasnya. Menjadi suatu hal yang tidak terlalu mengada-ada kalaupun kemudian mempertanyakan, misalnya, apakah bentuk kata kerja itu―meminjam istilah linguistik―“transitif” atau “intransitif”. Begitu pula halnya jika kata kerja itu akan kita pakai untuk sebuah kalimat; apakah akan menjadikannya kalimat aktif atau kalimat pasif?
[Dengan deskripsi yang saya anggap paling sederhana penjelasan mengenai hal itu adalah demikian: (1) Jika kata kerja-nya itu transitif dan ditempatkan menjadi kalimat aktif (“aktif-transitif”), karena memperhitungkan “objek” (yang dalam konteks ini analog dengan society/konsumen), ada semacam kepedulian terhadap konsumen yang kemudian berusaha dirangkulnya tanpa terjebak untuk jatuh di bawah bayang-bayang “selera” konsumen itu sendiri; kebalikannya adalah (2) “pasif-transitif”. Di sini sastrawan/produsen yang seakan-akan menjadi “objek”. Kepeduliannya terhadap konsumen adalah justru dengan bertekuk lutut di bawah kekuasaan konsumen; sementara untuk yang (3) “aktif-intransitif”, tidak begitu mempedulikan keberadaan konsumennya, bahkan sama sekali mengabaikannya (atau boleh jadi hanya ditujukan bagi kalangan tertentu atau mungkin hanya untuk pencapaian katarsis dirinya sendiri), yang menutup kemungkinan adanya kompromi; semacam pandangan “sastra untuk sastra”, dan yang biasanya diperjuangkan di sini adalah target pencapaian wilayah estetis untuk mengejar inovasi, pembaruan, dls.; dan (4) “pasif-intransitif”, ini yang saya anggap paling celaka, karena hanya akan menjadi sebentuk kekenesan atau kalimat imperatif sebagaimana yang telah saya singgung di muka.]
Hal-hal tersebut menjadi perlu untuk dikedepankan mengingat kontekstualisasinya kemudian dengan produk yang dihasilkan dan kedudukan produk tersebut di tengah konsumennya. Memang boleh jadi betul, dilihat dari satu sisi, seorang sastrawan, dengan kapasitas yang dimilikinya, tidaklah dituntut untuk selalu bertolak dan dideterminasi oleh hal-hal semacam itu (karena produk yang dihasilkannya pun bukanlah semata “barang belanjaan”); bahwa, yang lebih diperlukan darinya adalah berkarya dan terus berkarya.
Namun, di sisi lain, disadari atau tidak, itu semua merupakan beberapa pilihan yang harus siap dihadapi―dengan sekian konsekuensinya―ketika ia memutuskan turut bermain untuk memproduksi teks-teks sastra. Terlebih dalam kaitannya dengan masalah alienasi sastra, yang pada kenyataannya pihak sastrawan pun mengambil peran yang cukup signifikan dalam menciptakan dan mempertebal dindingnya; sementara di satu pihak, sebagian besar masyarakat kita agaknya memang sudah cenderung terjauh/menjauhkan diri dari dunia imaji yang abstrak, mungkin sebagai akibat dari pola hidup yang telah tertata rapi oleh “rezim pembangunan” yang selama ini memang seperti menawarkan (dan sekaligus membius) mereka dengan dunia-dunia konkret yang materialistik, dengan perhitungan ekonomis profit-defisit yang serba kebendaan; di lain pihak, sebagian besar sastrawannya pun tampaknya masih terlalu rajin untuk “mendefamiliarisasikan” dirinya sendiri dengan berkutat di wilayah “kepelikan estetika” yang seringkali tidak (atau belum) dipahami/terpahami oleh realitas masyarakat kita yang semacam itu.
Ya, apa yang kita lakukan semuanya mungkin beratasnamakan cinta. Tetapi, untuk menumbangkan “rezim alienasi sastra” ini, melakukannya hanya karena perasaan cinta semata agaknya belumlah cukup. Lebih dari itu; persoalannya adalah justru bagaimana kita (harus) bisa membagi dan menularkan perasaan cinta yang kita punya itu pada “dunia”.
²²²