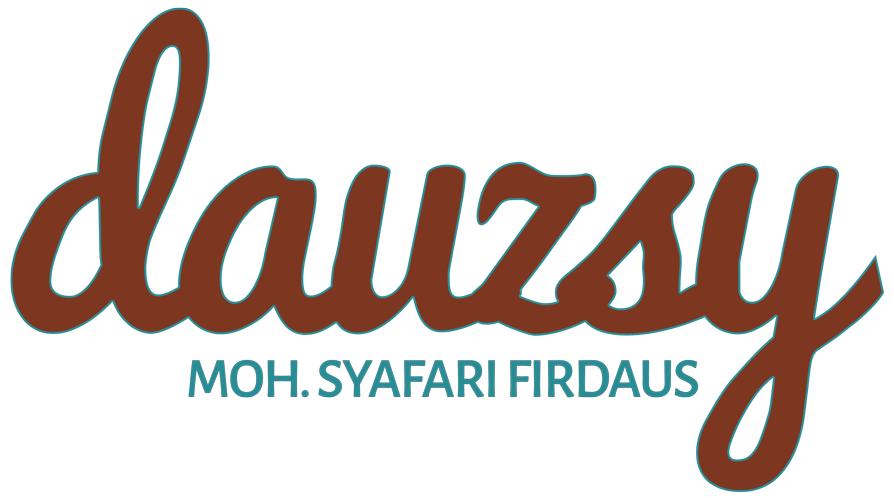Ada banyak kalangan yang menyebut bahwa keruntuhan Rezim Orde Baru oleh Reformasi Mei 1998 yang lalu, pada konteks tertentu menyimpan kemiripan sebagaimana halnya ketika Rezim Orde Baru menggulingkan Rezim “Orde Lama” (Demokrasi Terpimpin) di tahun 1966. Kedua peristiwa tersebut menunjuk pada satu fenomena: “kekuasaan yang tumbang oleh kekuatan rakyat!”
Sebagaimana generasi ‘66, pada reformasi ‘98 pun ditandai pula oleh melubernya rakyat dan mahasiswa ke jalan-jalan, menggedor dan menjebol dinding tebal tirani-kekuasaan beserta segenap sindikasinya, untuk menuntut kembali tegaknya kedaulatan rakyat. Jika generasi ‘66 yang dibakar dengan semangat “amanat penderitaan rakyat” meneriakkan yel-yel Tritura: bubarkan kabinet, bubarkan PKI dengan segala antek-anteknya, turunkan harga; maka, dengan semangat yang sama pula, reformasi ‘98 memekikkan: turunkan Soeharto, segera adakan Sidang Istimewa MPR, cabut 5 paket UU Politik! Secara permukaan, pembeda yang tampak cukup signifikan dari munculnya gerakan rakyat yang dinahkodai oleh barisan mahasiswa itu terletak di tingkat pemicunya. Gerakan ‘66 disulut oleh “sentimen ideologis”, yang kemudian meledak setelah peristiwa Gestapu; sementara reformasi ‘98 berkobar karena “sentimen ekonomi”, bermula dari krisis moneter berkepanjangan dan ditambah dengan semakin melejitnya kebobrokan mental dan moral para birokrat dan pejabat di jajaran elit-kekuasaan yang begitu hobi ber-KKN ria.
Akan tetapi, di tengah-tengah berkecamuknya sekian peristiwa yang menggelembung itu, di antara keriuhan perbincangan perihal resesi ekonomi global, isu-isu keadilan dan hak azasi, melambungnya harga sembako, pendeklarasian “partai-partai reformasi”, pengusutan harta kekayaan negara yang sempat dicolong di sana-sini, keberadaan sebuah dunia yang mendapatkan sebutan sastra, kekusastraan, kiranya masih juga terus terjepit di tengah pusaran gelombang dan arus besarnya. Sebagai bagian yang tersimpan dalam wacana kebudayaan, bahkan diyakini pula sebagai salah satu penggerak peradaban, di sini sastra tampaknya masih belum mampu untuk berucap lantang di tengah-tengah realitas yang mesti disikapinya, di antara “dunia” yang notabene adalah menjadi gagasannya. Hingga saat ini, sastra nyatanya seakan masih hanya berbisik pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri.
Keterjepitan sastra di tengah kancah reformasi kita hari ini, agaknya boleh dibilang berbanding terbalik dengan fenomena sastra ‘66 yang konstelasi peristiwanya itu nyaris serupa sebagaimana yang tadi telah disinggung di muka. Dalam upaya perjuangan untuk menuntut kembali tegaknya kedaulatan rakyat, kabarnya, ketika itu sastra mampu ambil bagian untuk muncul di garis terdepan. Begitu pun halnya dengan aksi dan eksistensi pada sastrawannya yang, syahdan, tidak cuma sekadar ada untuk kemudian dipandang sebelah mata. Deklarasi “Manifes Kebudayaan”, misalnya, boleh disebut sebagai momentum penting sebagai upaya penyikapan dari (sebagian) sastrawan/seniman pada konteks saat itu untuk menentukan gerak serta langkah mereka. Sederet karya yang kemudian diidentifikasikan kanonik yang kini tersimpan di dalam khazanah kesusastraan kita, dan demikian pula halnya dengan sejumlah nama sastrawan yang sampai saat ini masih tetap bercokol di jajaran elit-sastra Indonesia, boleh dipandang turut dibesarkan dan terdongkrak dari situasi semacam ini. Ya, sementara sastra dalam fenomena reformasi kita ini?
Betul, hingga saat ini pun mungkin sudah tidak lagi terhitung jumlah karya-karya sastra yang bertemakan reformasi, yang lahir dari situasi dan kondisi kekinian Indonesia; baik itu yang kemudian dibacakan (dalam beberapa kesempatan, pada momen atau acara-acara tertentu, terutama pada saat bergelarnya suatu demonstrasi, kita mungkin kerap mendapati dan disuguhi oleh pembacaan puisi), yang dipublikasikan di media-media cetak (majalah Horison sempat menurunkan sajak-sajak bertajukan reformasi, Republika bahkan kini mentiteli ruang puisinya dengan “Sajak-sajak Peduli Bangsa”), yang telah dibukukan (antologi Tangan Besi yang digalang oleh Forum Sastra Bandung, misalnya), ataupun bahkan setumpuk karya lain yang hingga saat ini masih hanya tersimpan di laci-laci meja para penulisnya. Akan tetapi, dari sekian banyak karya (sastra) yang lahir itu, sebagian besar agaknya masih dirasa belum mampu menyentuh, apalagi menyatu, dengan ruang (kesadaran) publik sebagaimana yang diharapkan; ia seakan kembali pecah berkeping dan menjadi serpihan-serpihan yang berserakan begitu saja. Terkadang ia pun berkesan hanya berupa histeria dan euphoria kata-kata, lebih mirip retorika dan slogan-slogan politis yang sekejap menggelegar untuk seterusnya kembali lenyap dalam kesenyapan. Bahkan, ada yang sempat mensinyalir, dengan karya-karyanya itu sebagian penyair justru seperti hanya sekadar berperan sebagai “penumpang gelap” reformasi.
Tentu, memang ada beberapa faktor mendasar yang kemudian membedakan antara fenomena sastra ‘66 dengan fenomena sastra dalam kancah reformasi kita hari ini. Situasi yang terjadi serta apa yang diperjuangkannya memang boleh jadi sama, namun dalam konteks “realitas sosiologis” yang dihadapinya menunjukkan perbedaan yang cukup tajam; pada problem yang berkaitan dengan konstelasi “politis-ideologis”, misalnya.
Fenomena sastra ‘66 boleh jadi bisa mencuat ke permukaan karena ditandai oleh adanya bentuk perlawanan dengan rival yang cukup jelas. Pada daratan politis-ideologis itu, di sini muncul “Manikebu” yang berdiri di belakang “humanisme universal” versus “Lekra” yang mengusung jargon “politik sebagai panglima”. Masing-masing kubu yang pada saat itu didukung oleh sejumlah media cetak bisa dengan cukup leluasa untuk menghujani publik dengan sederet wacana yang dikedepankannya; membombardirnya dengan polemik, kontroversi (bahkan hujatan demi hujatan), yang pada akhirnya mampu menggiring dan menggelembungkan sastra (kesenian dan kebudayaan pada umumnya) sebagai isu-isu sentral pula. Kondisi demikian menjadi efektif untuk mengasilkan semacam “pembesaran” dan mengidentifikasikan akan adanya eksistensi dari para sastrawan/senimannya. Sementara pembesaran dan hadirnya eksistensi itu sendiri menjadi sangat mungkin untuk menjelma “legenda” yang dicatat sebagai sebuah “sejarah”. Maka, sebagaimana yang kita kenal sampai hari ini, fenomena sastra ‘66 dengan gilang-gemilang bisa berhasil mencatatkan dirinya sebagai sebuah generasi, angkatan yang tidak saja diakui, tetapi juga dilegitimasi (untuk lebih lengkapnya, boleh ditengok Prahara Budaya, D.S. Moelyanto dan Taufik Ismail, Mizan, Bandung, Maret 1995).
Berbeda halnya dengan fenomena sastra kita hari ini; tidak terbaca (setidaknya dengan cukup jelas) adanya rival di tingkat yang sejajar (=kalangan sastrawan/seniman) sebagaimana yang tampak pada fenomena sastra ‘66 itu, menyebabkan tidak memunculkan pula perbenturan di tingkat konseptual; kendatipun Rezim Orde Baru yang dijadikan sasaran fokus perlawanan memiliki pula, sebut saja, para “seniman Golkar”–paling-tidak dari mereka yang dulu kerap terlihat “urun-manggung” dalam kampanye, misalnya (kalaupun di sini boleh ditarik satu analogi, para seniman yang tergabung dalam Lekra itu pun dulu diidentifikasikan berafiliasi dengan PKI). Maka adalah menjadi suatu hal yang wajar pula jika dalam konteks reformasi kita hari ini tidak ada “pertarungan gagasan” yang pada akhirnya mampu mendongkel isu-isu di seputar sastra (kesenian/kebudayaan) ke wilayah yang lebih luas, sebagaimana layaknya isu-isu politik, sosial, ekonomi, keadilan, atau hak azasi yang begitu riuh menggelombangkan suara reformasi. Di sini, para sastrawan (dan juga para seniman/budayawan pada umumnya), paling-tidak yang saya cermati hingga saat ini, seolah masih belum menemukan bahasa dan ruang aktualisasinya. Mungkin hanya segelintir saja, yang itu pun agaknya belum sepenuhnya terakumulasikan menjadi karya sastra.
Sementara di sisi lain, sebagaimana yang mungkin masih kerap kita rasakan, sastra (kesenian/ kebudayaan) untuk sebagian besar masyarakat kita pada saat ini agaknya masih juga dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif; belum bisa membumi. Entah, apakah hal ini pada awalnya diakibatkan oleh ulah para sastrawannya itu sendiri yang (mungkin) masih seringkali terlalu arogan untuk hanya bergelut di wilayah “kepelikan pencarian estetika” yang hasilnya itu kerap sangat sukar untuk dipahami/terpahami, sehingga sebagai konsekuensi logisnya sastra pun harus berbesar hati untuk dialienasikan/teralienasikan oleh publiknya; ataukah, kondisi semacam ini muncul dikarenakan masyarakat kita sendiri yang memang sudah kadung telanjur menjauhkan diri dari dunia-dunia imaji yang abstrak, sebagai akibat dari pola hidup yang telah tertata sedemikian rupa oleh “rezim pembangunan” yang selama ini memang seperti menawarkan dan sekaligus membius mereka dengan dunia-dunia konkret yang materialistik, penuh dengan kalkulasi ekonomis profit-defisit yang serba kebendaan dan sangat permukaan?
Kondisi semacam ini pun bukan hanya kurang menguntungkan, tetapi adalah sungguh celaka bagi sastra. Ketika pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia, terutama dalam satu dekade terakhir, justru tengah bertumpu pada “satrsa koran”, sementara gelombang krisis moneter yang terus berpusing di negeri ini pun harus melambungkan pula harga kertas koran yang pada akhirnya memaksa koran-koran itu untuk melakukan rasionalisasi (penghilangan sebagian halamannya, dls.), dengan tidak didukung oleh kondisi sosiologis sastra di tengah masyarakatnya sebagaimana yang diasumsikan tadi, maka di sini menjadi bisa dimaklumi jika bentuk perwujudan dari upaya rasionalisasi yang dilakukan koran-koran tersebut–sebagai institusi profit yang berada dalam penguasaan jaring-jaring kapitalistik, ia dituntut untuk sedapat mungkin mencermati pasar agar bisa tetap hidup–adalah memilih untuk menggusur sebagian atau bahkan menumbalkan halaman-halaman sastranya (selain, konon, halaman-halaman sastra ini kabarnya menyedot alokasi dana yang tidak sedikit), yang notabene sebenarnya praktis hanya turun satu minggu sekali.
Kaitan dengan masalah goyahnya media pengkabar sastra ini pun agaknya bisa ditarik pula sebagai parameter pembeda dengan fenomena sastra ‘66. Kali ini sastra justru semakin berada dalam posisi yang serba sulit, baik itu untuk bisa lebih mengkampanyekan keberadaan dirinya di tengah publik (sebagaimana yang sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun belakangan) maupun untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya dalam konteks kekinian, terlebih lagi jika ia ingin berbaur untuk turut berpartisipasi mencorongi suara-suara reformasi.
Kendatipun keberadaan sastra di tengah kancah reformasi kita hari ini dirasakan kian terjepit dan berada dalam posisi yang serba sulit, namun dalam hal ini bukan lantas berarti sastra menjadi tidak akan (pernah) bisa pula menyuarakan dirinya dalam upaya untuk menyikapi realitas beserta segenap kompleksitas persoalan sebagaimana yang tengah kita alami pada saat ini. Seorang kawan sempat berujar, para sastrawan kini mungkin masih merasa perlu untuk mengendapkan setiap hasil pencerapan yang diperolehnya, sebelum ia kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya sastra. Boleh jadi, karya itu sendiri tidak muncul saat ini, tapi pada suatu hari nanti. Ya, bisa dipahami, karena bagaimanapun karya sastra bukanlah sesuatu yang instan, langsung jadi. Bukan pula cuma sekadar media katarsis; namun lebih dari itu, ia pun adalah medan kontemplatif.
Jika kita melirik satu tesisnya Lucien Goldmann yang menyebut bahwa momen-momen krisis sosial yang besar biasanya akan bisa memberi kriteria dan karakter kuat (kanon) pada karya sastra yang kemudian dihasilkannya, maka mungkin demikian pula dengan harapan kita untuk karya-karya sastra Indonesia yang pada suatu hari nanti, mudah-mudahan, akan lahir itu. Bukan suatu hal yang terlalu berlebihan pula kiranya jika kita pun kemudian berharap akan bisa membaca karya-karya sastra Indonesia sebagaimana, misalnya, Dr. Zhivago-nya Pasternak yang juga merekam saat-saat terjadinya Revolusi Bolsyewik Rusia.
Terlepas dari soal apakah realitas reformasi kita hari ini menyimpankan potensi dan pretensi kanonik atau tidak, namun kelahiran dan kehadiran karya-karya sastra tersebut sekurang-kurangnya mungkin akan bisa menghindari munculnya anggapan di kemudian hari bahwa sastra generasi reformasi adalah “angkatan sastra yang tergusur”.
²²²