Kalaupun harus disebut bahwa musik adalah salah satu genre seni yang nasib hidupnya lebih beruntung di Indonesia, mungkin tidaklah terlalu berlebihan. Dilihat dari segi pertumbuhan dan perkembangannya, seni musik boleh dibilang sudah beberapa tahap lebih maju ke arah garis kemapanan. Seni musik agaknya sudah cukup kokoh dalam memancangkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat: mampu mengartikulasikan dirinya, hingga ia pun pada akhirnya bisa menggelembung bersama dunia industri untuk menjadi sebuah institusi profit, energi kapital, yang sangat menjanjikan.
Kondisi demikian tampaknya sangat jauh berbeda dengan fenomena yang tersimpan di seputar genre-genre seni lainnya yang juga hidup di Indonesia. Terlebih kalau harus dibandingkan dengan seni sastra atau teater, misalnya, yang keberadaan dan nasib hidupnya masih kerap terongkang-ongkang. Begitu pun dengan nilai ekonomis yang melekat pada dirinya, yang nyaris harus selalu mengalami defisit. Maka cukup bisa dimengerti kiranya kalaupun kedua genre tersebut masih kerap dikategorikan sebagai “keluarga seni pra-sejahtera”.
Maraknya industri rekaman dan melimpahnya produksi album lagu di Indonesia dalam satu dekade belakangan (terutama ketika era digital makin berkuasa), mungkin bisa kita tarik sebagai indikasi paling permukaan untuk menunjuk bagaimana eksis dan artikulatifnya dunia musik kita itu. Betul, dengan jumlah penduduk yang lebih dari 220 juta, Indonesia adalah market yang sangat potensial.
Dengan orientasi market yang sangat beragam dan cukup menggiurkan itu, maka tidaklah mengherankan jika ada begitu banyak produser dan perusahaan rekaman yang malang melintang untuk menyemarakkannya, tanpa terlalu dihantui oleh rasa cemas dengan soal bagaimana kalkulasi ekonomisnya di kemudian hari. Alhasil, boleh kita lihat, corak, ragam, atau kelir musik macam bagaimana yang tidak ditemukan di Indonesia. Nyaris segala ada. Tinggal pilih. Suka-suka.
Dalam beberapa hal, kondisi seperti itu memang cukup menggembirakan. Namun di sisi lain, mesti terbetrik pula sejumlah hal yang kiranya patut untuk dicermati. Paling tidak, masalah yang berkenaan dengan kualitas—baik itu yang berkenaan dengan soal teknis penggarapan lagu, vokal, maupun produk lirik yang kemudian dihasilkan oleh para musisi kita—kiranya masih tetap perlu untuk kita agendakan sebagai bahan perbincangan. Meskipun terkesan klise, namun hal ini tetap merupakan permasalahan mendasar yang masih sangat layak untuk diperhatikan dengan sangat serius. Terlebih lagi dalam konteks di Indonesia, yang hingga saat ini masih juga tetap miskin—kalaupun tidak boleh dibilang “tidak ada”—dengan para kritikus musik (dan juga kritikus seni pada umumnya) yang berkenan untuk bergelut dan sekaligus ambil bagian untuk terus melakukan penilaian secara serius terhadap produk musik Indonesia.
Hampir tidak muncul wacana kritis bagi produk musik kita itu. Maka, tidaklah terlalu mengejutkan jika satu implikasi yang muncul kemudian adalah tumbuhnya suatu tradisi yang mengesankan untuk cukup memandang masalah kualitas hanya dengan sebelah mata, tidak terlalu menjadi bahan pertimbangan yang perlu untuk dipertaruhkan. Bahkan, tidak sedikit pula yang dengan secara sadar memang sengaja mengabaikannya.
Akan bisa ditemukan banyak contoh untuk menunjuk hal itu. Fenomena semacam ini biasanya tampak benar pada produk musik yang terlahir dari seorang penyanyi yang sebenarnya bukan—atau belum pantas jadi untuk menjadi—penyanyi. Tanpda mengurangi rasa hormat dengan segala usaha yang telah dilakukan, mereka harus menjadi penyanyi karena di-up grade, atau karena memang memaksakan diri untuk menjadi penyanyi.
Dari soal legalitas, apa yang mereka lakukan itu memang sah-sah saja adanya. Namun jika harus memakai tinjauan profesionalitas, hal ini agaknya merupakan sebuah “keajaiban” karena bisa menyandang predikat penyanyi/vokalis dari mutu suara seadanya, bahkan masih boleh terbilang untung kalaupun kemampuannya itu hanya bisa setingkat pas-pasan. Yang kemudian justru menjadi dilematis adalah ketika produk musik yang sesungguhnya tidak cukup berkualitas semacam itu nyatanya tetap dilirik dan diincar oleh publik. Bahkan, tidak jarang ada yang bisa sampai mencapai tingkat booming di pasaran.
Dalam kalkulasi ekonomis, booming semacam itu tentu saja menguntungkan. Hanya saja, dengan adanya kondisi itu pula yang kiranya telah memungkinkan, kebiasaan untuk mengabaikan aspek kualitas menjadi semakin membudaya. Memang wajar, sebagai bagian dari industri khas kapitalis yang profit oriented, adanya energi kapitalistik seperti itu tentu adalah yang paling utama dicari. Toh, kenapa pula harus repot-repot menjajakan kualitas jika segalanya bisa terselesaikan ketika sebuah produk yang ditawarkan sudah sanggup menutupi segala cost yang dikeluarkan?
Pada konteks ini, musik pada akhirnya seolah hanya disikapi sebagai barang dagangan: ia hadir tidak lagi dalam kapasitasnya sebagai sebuah bentuk seni yang sesungguhnya bisa menawarkan begitu banyak energi lain di luar keuntungan material/kapital.
²²²
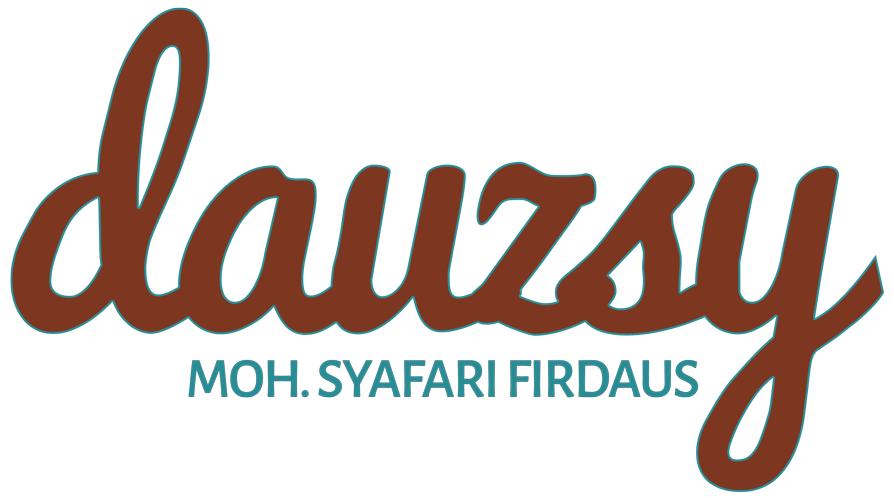

4 komentar
setuju mas.. tp memang pd akhirnya tidak bisa dipungkiri kebutuhan material yg dicari..
yg jadi permasalahan.. kapitalismenya.. hehehehe.. dunia.. dunia..
MARI BERKARYA
Bagus artikelnya,salute!
Saya setuju dengan Mas Remy di atas. Tapi masih segar dalam ingatanku bahwa industri musik di Indonesia berjalan sejalan dengan politik nasional, yakni mengabaikan Indonesia Timur. Buka sejarah musik kita, sangat jarang dibicarakan grup band dari Timur. Siapa yang mau peduli mereka? Padahal musik itu univeresal, tidak parsial. Betul to. Stef Tokan