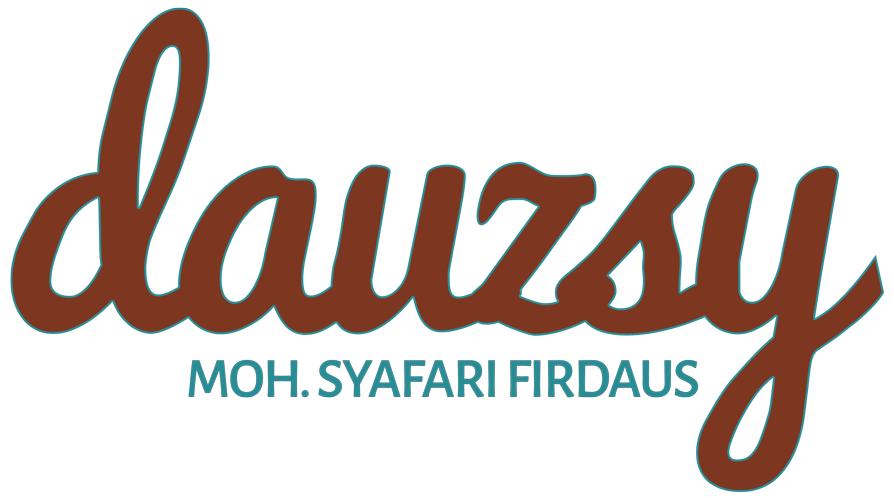Seni berarti menghancurkan persepsi dari yang tadinya otomatis menjadi tidak otomatis; tujuan dari imaji bukanlah untuk menghadirkan makna dari objek yang dideskripsikan pada pemahaman kita, melainkan untuk membentuk suatu persepsi khusus dari objek tersebut. (Victor Shklovsky)
Saya akan memulai perbincangan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana: “Apakah karya sastra—atau karya seni pada umumnya—harus selalu dipandang sebagai sesuatu yang bermakna, bernilai agung dan adiluhung?”
Jika kita mengikuti pola pandangan “tradisional-formal”, maka kita pasti akan menemukan keyakinan semacam ini. Eksistensi dari nilai kebermaknaan akan menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar dan harus bisa dipenuhi oleh sebuah karya. Kandungan nilai makna inilah yang kemudian akan menentukan tingkat keagungan dan keadiluhungannya.
Meski tidak secara verbal menganggapnya sebagai sesuatu yang agung dan adiluhung, namun pandangan yang meyakini bahwa setiap bentuk karya seni—sastra dalam perbincangan kita—menyimpankan semacam ”makna” tertentu di dalam dirinya, sebenarnya tersirat pula dalam sejumlah referensi teoritis yang ada. Adanya pendapat yang menyebut bahwa sastra merupakan perpaduan antara sesuatu yang bermanfaat dan yang menyenangkan (qui miscuit utile dulci) (Horatius); adalah sebuah wilayah yang penuh dengan harta kekayaan berupa pengertian manusia, pandangan perseorangan, dan sensivitas yang menonjol (Robert C. Pooley); jalan keempat menuju kebenaran (Aristoteles); merupakan alat untuk menerima dan memberikan penerangan, enlightenment (Danarto), mungkin bisa lebih mempertegas eksistensi “makna” sebagaimana yang dimaksudkan.
Tinggal kini pertanyaannya adalah, apakah karya sastra itu, harus selalu dipahami maknanya? Dan, bagaimana kita, sebagai pembaca, seterusnya mesti memandang dan menyikapi kebermaknaan karya tersebut?
ll
Ada semacam pemeo yang kadung berkembang di kalangan masyarakat umum kita bahwa yang kemudian disebut karya sastra adalah sebuah bahan bacaan yang “berat” dan “sulit”: apa yang diketengahkannya terkadang ngejelimet dan selalu penuh dengan ungkapan-ungkapan simbolistik yang terkadang memusingkan untuk ditafsirkan, sehingga kerap pula menyukarkan pembacanya untuk bisa mengerti dan memahami konteks “makna” yang terkandung di dalamnya.
Pemeo semacam ini memang tidak salah, namun tidak juga sepenuhnya benar. Karya sastra memang ditulis dengan suatu “cara tertentu” dan juga dengan tujuan tertentu: mengedepankan suatu gagasan. Untuk mencapai tujuannya itu, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pengarang adalah dengan mengolah dan memanfaatkan kekayaan yang tersimpan di dalam bahasa yang menjadi medium utama karya sastra. Dari mulai fonem (huruf), morfem (imbuhan), diksi (pilihan kata), semantik (arti kata), sintaksis (kalimat), hingga kesatuan antarparagraf yang membangun teks (wacana) secara keseluruhan, biasanya akan sangat diperhatikan keberadaannya oleh pengarang. Begitu pun halnya dengan aspek ritma, rima, matra, bunyi/akustik, aliterasi, asonansi, ataupun gaya bahasa yang muncul sebagai bagian dari kekayaan bahasa itu, akan bisa dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk menghasilkan efek-efek estetik guna pencapaian tujuan artistik karya, misalnya.
Bangunan karya pun akan semakin bertambah kompleks ketika gagasan yang ingin dituangkan kemudian dituturkan dengan teknik dan penggayaan tertentu. Hal inilah yang telah memungkinkan karya sastra menjadi seolah ngejelimet, ruwet, dan sukar untuk dipahami. Sekadar contoh, dari segi teknik, ada yang disebut dengan defamiliarisasi, yaitu untuk membuat objek yang dideskripsikan menjadi “sulit untuk dikenali” atau menjadikannya seolah-olah tidak/di luar kelaziman. Untuk mengungkapkan rasa cinta seseorang, misalnya, di dalam sebuah karya sastra mungkin belumlah akan dirasa cukup jika hanya diungkapan dengan kalimat, “Aku cinta padamu”. Malahan boleh jadi hal itu akan dibahasakan dengan sangat panjang, dideskripsikan beralenia-alenia, dengan cara melipir, malapah gedang. Realitas yang dideskripsikan dan diceritakannya pun mungkin bukanlah tentang romantisme dengan idiom-idiom kisah-kasih asmara, melainkan yang justru dihadirkannya adalah tentang kekerasan, misalnya. Bahkan, menjadi akan sangat mungkin jika kalimat “Aku cinta padamu” itu sendiri sama sekali tidak pernah terucapkan secara verbal di sana.
Di sinilah terjadinya proses penghancuran persepsi pada pemahaman kita oleh karya seni (sastra), dari yang tadinya otomatis menjadi tidak otomatis, sebagaimana yang dimaksudkan Shklovsky dalam pernyataannya yang telah saya kutip untuk membuka tulisan ini. Jika kita melihat hal-hal tersebut, memang akan tampak terkesan jika karya sastra itu rumit. Akan tetapi, apakah harus serumit itu pula ketika kita berupaya untuk memahami dan memaknainya?
Dalam tinjauan studi akademis, memang ada tuntutan untuk bisa mengkaji dan menganalisis segala aspek yang tersimpan di dalam karya sastra secara tuntas. Dengan menggunakan perangkat teori yang tak kalah ruwetnya pula, semua aspek itu harus bisa dibongkar dan dipetakan. Proses interpretasi (pemahaman dan pemaknaan) sebisa-bisanya harus mampu dijabarkan secara analitis, rasional, dan objektif.
Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan apresiasi yang lebih bersifat individual, dalam arti, kita memposisikan diri bukan sebagai peneliti sastra, namun hanya sebatas pembaca yang menyikapi karya sastra sebagai bahan bacaan semata. Dalam hal ini, tidak ada keharusan yang menuntut kita untuk bisa membongkar dan memetakan semua aspek yang ada di dalam sebuah karya secara tuntas. Bahkan, boleh jadi proses interpretasi tidak perlu dilakukan sama sekali, karena kita tidak dituntut pula untuk sepenuhnya memahami dan memaknainya. Mungkin hanya sebatas resepsi (penerimaan/tanggapan) subjektif kita, yang itu pun tidak menuntut sebuah penjabaran analitis-rasional-objektif. Di sisi ini, tanggapan yang hanya sebatas mengedepankan logika: “saya paham jika saya tidak memahami karya yang saya baca,” masih akan bisa berterima. Begitu pun jika kita kemudian menarik kesimpulan untuk memahami “ketidakpahaman” itu sebagai “kepahaman” kita terhadap karya sastra yang bersangkutan.
Akan sama halnya ketika cara pandang seperti itu kita pakai pula untuk menyikapi nilai kebermaknaan karya sastra. Persoalan apakah kita akan bisa menemukan makna (literal) yang terkandung di dalamnya atau tidak, sebenarnya akan bisa kita pandang bukan sebagai suatu hal yang terlalu penting. Bahkan, masih akan sangat mungkin jika kita sama sekali mengabaikannya. Hal ini bisa dimungkinkan karena kandungan nilai makna itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat abstrak, sangat interpersoanal, bersifat proses, dan tidak bisa terbahasakan secara verbal: ia mungkin sebenarnya telah tercerap oleh kita, namun tersimpan di alam bawah sadar kita. Pada konteks ini, kita mungkin saja tidak akan memahami atau menemukan makna yang tersimpan di dalam sebuah karya sastra begitu kita selesai membacanya; tetapi boleh jadi kita justru akan mendapatkan relevansi, aktualisasi, dan kontekstualisasinya jauh hari kemudian, ketika kita tengah berada dalam sebuah kondisi tertentu yang mungkin akan kembali mengingatkan kita pada apa yang telah kita baca itu.
Meskipun kita kemudian mengabaikan (atau tidak bisa menarik) makna dari karya sastra yang kita baca itu, sebenarnya masih akan ada banyak hal yang tetap bisa dapatkan dari hasil membaca karya sastra. Paling tidak, jika kita memang merasa tidak memahami dengan apa yang kita baca, mencoba untuk bisa memahami mengapa kita tidak memahami itu pun sudah merupakan sesuatu hal yang sangat berharga pula. Selain itu, hal yang bisa kita dapatkan dari hasil membaca karya sastra adalah pengembaraan dan pengayaan imaji; mungkin juga bisa menemukan semacam “pengalaman estetis” (seperti ketika kita menikmati warna-warni dalam lengkung pelangi, misalnya), sesuatu yang “sublim”, yang mungkin hanya bisa terjaring oleh sensitivitas rasa, yang kita sendiri tidak pernah tahu apa itu sebenarnya.
Namun, kalaupun persoalannya tetap mengganjal pada konteks kebermaknaan, yang perlu kita renungkan kemudian adalah, bukanlah segala sesuatu itu akan selalu bermakna? Bukankah “ketidakbermaknaan” sekalipun masih mempunyai nilai, dan masih mungkin untuk bisa kita pandang sebagai makna itu sendiri? Dengan kata lain, di dalam karya (seni) sastra, makna (literal) bukanlah segalanya, karena segalanya akan sangat berpotensi untuk bisa menjadi bermakna, terlebih jika kita memang berkenan untuk mau memaknainya.
Jika kita menyikapi karya sastra dalam konteks seperti ini, niscaya tidak ada lagi karya sastra yang akan dipandang sulit atau berat. Toh, pada akhirnya sesulit dan seberat apapun karya itu sebenarnya masih akan tetap bisa dihadapi dan disikapi dengan cara yang ringan dan sederhana. Cara pandang dan penyikapan seperti inilah yang justru kita perlukan, agar karya sastra (dan karya seni pada umumnya) bisa dibaca dan dinikmati tanpa terbebani oleh kebermaknaannya yang hanya bersifat “klangenan” semata.
²²²