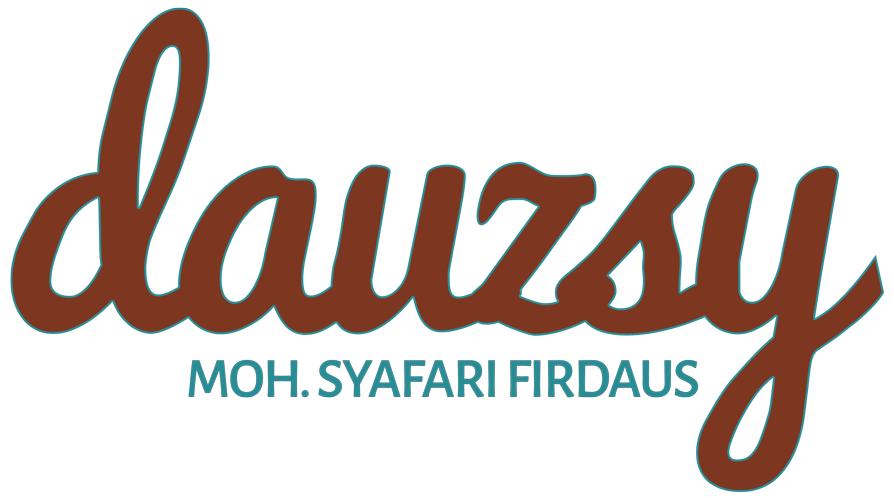Barangkali memang tidak terlalu berlebihan kalaupun kemudian ada yang beranggapan bahwa karya seni harus selalu siap untuk berhadapan dengan semangat zaman yang tak kenal ampun. Sebagai sebuah entitas yang menempatkan “realitas” (dalam konteks yang sangat luas; universe) sebagai pijakan dan rujukan gagasannya, karya seni mencoba untuk mencermati, mencerap, menerjemahkan, dan sekaligus menyikapi realitas dengan segala gejala dan fenomenanya sebagai sebuah “dunia baru”, dalam berbagai bentuk dan artikulasi, yang pada akhirnya ia akan (di)kembali(kan) pada realitas itu sendiri. Pada titik inilah karya seni menjadi sangat mungkin untuk berhadapan dengan semangat zaman yang tengah bergerak dalam realitas yang dimasukinya.
Kendatipun karya seni berkaitan erat dengan realitas, namun apa yang tertuang di dalamnya tidaklah identik dengan realitas itu sendiri. Ia bukan semata pencerminan (mimesis) dari realitas—sebagaimana pemahaman Plato—yang kemudian bisa dipandang sebagai realitas yang sebenar(-benar)nya. Ketika suatu realitas sudah dipindahkan menjadi sebuah bentuk karya seni, maka pada saat itu ia sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang sama sekali lain. Hal ini bisa dimungkinkan karena karya seni selalu mem-berikan peluang yang sangat lebar untuk menghadirkan “fiksionalisasi” (pengurangan dan/atau penambahan sesuatu pada realitas yang menjadi objek, misalnya), yang muncul bersamaan dengan adanya partisipasi dan peran serta “imajinasi” dan “fantasi” dari si senimannya.
Sementara itu, karena karya seni mengedepankan dan mengartikulasikan realitas, serta dalam konteks sosialisasinya kemudian ia akan berada di tengah-tengah masyarakat luas, karya seni pun pada akhirnya dipandang berpotensi pula untuk dijadikan sebagai sebuah media yang cukup efektif untuk menyiarkan dan mengungkapkan berbagai hal. Leon Trotsky, misalnya, memandang bahwa dari perspektif historis-objektif karya seni akan selalu berperan sebagai abdi sosial dan berfaedah dalam sejarahnya. Karena itu, tidak jarang pula karya seni kemudian dipakai sebagai alat dan perpanjangan tangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu; disisipi dengan berbagai pretensi dan tendensi. Maka bisa kita tengok, karya seni kemudian tidak hanya disikapi sebagai sarana hiburan atau media katarsis semata, namun kerap dipandang sebagai gerbang perenungan juga; bukan hanya dijadikan alat untuk menanamkan nilai-nilai didaktik, melainkan dimanfaatkan juga sebagai media politis untuk mengusung “ideologi” atau kepentingan-kepentingan tertentu.
Akan tetapi, potensi yang sebenarnya cukup menguntungkan itu tampaknya tidak harus selalu menguntungkan karya seni. Bahkan sebaliknya, karya seni malah seperti menempati posisi yang serba sulit. Dalam konteks sosialisasinya, di alam ke-Indonesia-an kita sampai hari ini, karya seni agaknya nyaris selalu tersubordinasi; ia seakan begitu sulit untuk bisa berpijak dan berdiri sebagai dirinya sendiri. Karya seni pop-(uler), misalnya, kerap dituding sebagai korban kapitalisme, sekadar barang dagangan. Karya seni tradisi kerap hanya dimanfaatkan untuk memelitur eksotisme guna disuguhkan pada para wisatawan. Sementara, celakanya, karya seni yang kemudian diklasifikasikan sebagai, sebut saja, karya seni “yang serius” justru malah lebih banyak yang ditinggalkan oleh masyarakat.
Tidak hanya sampai di sana. Benturan yang kerap terjadi antara aspek “kebebasan mencipta” di satu pihak dengan realitas sosio-kultural masyarakat yang menjadi basis energi penciptaan dan sekaligus tempat sosialisasinya di pihak lain, menyebabkan relasi karya seni dengan masyarakat sosialisasinya itu terkadang menjadi kurang harmonis. Sebutlah, adalah masih tabu bagi karya seni untuk memasuki wilayah yang kemudian diidentifikasikan akan berkaitan dengan SARA atau norma/etika. Ini sepertinya sudah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap bentuk karya seni, karena jika tidak tinggal tunggu saja akibatnya; mungkin ia harus bersiap untuk menanggung nasib sebagaimana yang telah dialami oleh pementasan tari Samgita Sardono W. Kusumo, atau seperti kasus cerpen Langit Makin Mendung-nya Ki Panji Koesmin yang harus berakhir di pentas pengadilan, misalnya.
Dalam relevansinya dengan penguasa/kekuasaan, keberadaan karya seni—terutama dalam kaitannya dengan karya seni yang justru mengedepankan suara-suara kritis—bahkan kerap diperlakukan sebagaimana laiknya para perusuh yang patut ditertibkan. Pada masa pemerintahan Rezim Orde Baru, misalnya, tercatat ada begitu karya seni yang harus merelakan dirinya untuk dipetieskan atau bahkan diberangus sama sekali. Puisi-puisinya Rendra kerap menjadi langganan untuk dibredel, beberapa pementasannya Emha sempat digusur keamanan, atau F. Rahardi yang harus berbesar hati untuk berkenan dihentikan aparat saat ia membacakan Catatan Harian Seorang Koruptor, misalnya. Demikian pula halnya dengan sejumlah karya Pramudya Ananta Toer yang sampai saat ini masih terkubur hidup-hidup di negerinya sendiri. Itu baru secuil sumbangan dari genre sastra. Sebut saja, dari seni lukis, Hardi sempat menyumbangkan Presiden Indonesia Tahun 2001 untuk dianggap subversif; dari film, karena dianggap mengangkat problem korupsi di kalangan pejabat, Yang Muda Yang Bercinta-nya Sumandjaja untuk sementara harus dipetieskan; dari pang-gung teater, giliran Suksesi dan Opera Kecoa garapan Teater Koma yang harus mengalami nasib serupa, sampai yang terakhir adalah kasus pementasan Marsinah Menggugat-nya Ratna Sarumpaet yang tidak diperkenankan untuk dipanggungkan di beberapa tempat.
Hubungan yang kurang harmonis semacam itu agaknya lebih diakibatkan oleh masih kuatnya pandangan platonis yang cenderung menilai realitas yang tertuang di dalam karya seni identik dengan realitas nyata di alam keseharian. Pada kasus ini, aspek fiksionalisasi yang tumbuh dari imaji dan fantasi si seniman seringkali dilupakan. Betul, bahwa karya seni akan sangat mungkin mengusung ideologi tertentu, menyimpan tujuan-tujuan tertentu; namun yang mesti tetap diingat di sini adalah karya seni merupakan “produk rekaan” yang menyimpan sejumlah perbedaan mendasar dengan realitas yang berusaha diungkapkannya. Dengan kata lain, kalaupun karya seni mengusung suatu ideologi, kita sebenarnya harus bisa memandangnya sebagai “ideologi rekaan” pula. Di sini, tidak ada kemutlakan yang berdiri di belakang karya seni, hingga ia pun tidak menuntut agar realitas yang diungkapkannya harus diyakini sebagai sesuatu yang nyata dan sebenar-benarnya. Justru dengan “realitas rekaan”-nya itu, karya seni menjadi terbuka untuk bisa didekati dan didedah dengan berbagai penafsiran; sementara penafsiran merupakan suatu usaha ke arah pembelajaran.
²²
Lantas, bagaimanakah dengan nasib dan keberadaan karya seni di masa Orde Reformasi kita hari ini? Apakah dengan semangat demokrasi, keadilan, dan hak azasi yang diusungnya akan bisa membuka peluang pula untuk dapat mewujudkan ruang kebebasan mencipta?
Satu peristiwa yang menarik untuk disinggung dalam kaitannya dengan perbincangan kita ini adalah perihal keputusan untuk memberhentikan film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI yang biasanya selalu ditayangkan oleh seluruh stasiun TV kita di setiap tanggal 30 September. Alasan yang dikedepankannya, ketika itu oleh Menpen Yunus Yosfiah, film ini dipandang memuatkan tendensi pada adanya “kultus individu”.
Keputusan untuk tidak menayangkan film itu di seluruh stasiun TV sebagaimana biasanya boleh jadi memang bisa dipahami. Namun, alasan yang melatarbelakangi untuk tidak menayangkannya itulah yang tampaknya harus dipersoalkan. Pada kasus ini pun, dengan mengedepankan alasan tersebut setidaknya menandakan bahwa karya seni masih diidentifikasikan sebagai realitas konkret; seakan-akan tidak ada peran serta imajinasi dan fantasi yang turut bermain di dalamnya.
Betul, bahwa film garapan Arifin C. Noer itu pada awalnya lebih ditujukan sebagai, sebut saja, film bernuansakan “dokumenter-kesejarahan”; realitas yang diangkatnya didasarkan atas suatu peristiwa yang pernah terjadi, dan melibatkan sejumlah tokoh yang “konkret” adanya. Demikian pula, sebagai konsekuensi dari tujuan dokumenter dan kesejarahannya itu, film tersebut sepertinya memang telah diupayakan untuk digarap sedemikian rupa agar bisa “lebih mendekati” realitas dan peristiwa yang sebenarnya. Akan tetapi, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam film itu, di sela-sela “alur besar” perihal bagaimana usaha kup PKI yang divisualisasikannya, Arifin ternyata menyusupkan pula imajinasinya, paling-tidak hal ini diwakili oleh kehadiran “tokoh-tokoh rekaan”, seperti tokoh ibu (yang diperankan oleh Sopia WD) dan anaknya yang datang ke Jakarta itu, misalnya.
Kendatipun hanya sekadar sempalan, kehadiran tokoh-tokoh rekaan semacam itu sebenarnya telah memungkinkan untuk memberi indikasi bahwa film tersebut adalah “rekaan” pula. Secara teoritis hal ini bisa dijelaskan, meminjam bahasanya Aart van Zoest, adanya “atom-atom fiksional” (dalam konteks pembicaraan kita, tokoh rekaan ibu dan anak itu, misalnya), dalam hubungannya dengan yang nonfiksional (peristiwa kup PKI dan tokoh-tokoh “konkret” pelaku sejarahnya), akan menyebabkan seluruh “molekul teks” (dalam hal ini film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI) menjadi fiksional. Dengan demikian, sebagaimana yang sempat disinggung sebelumnya, hal ini menyiratkan bahwa pada hasil karya yang bernuansakan dokumenter-kesejarahan sekalipun sebenarnya tidak menyimpan kemutlakan yang kemudian menuntut agar realitas yang diangkatnya itu dilegitimasi sebagai sesuatu yang nyata dan diidentikkan dengan peristiwa se-sungguhnya.
Jika kita menggunakan sudut pandang seperti ini, alasan bahwa film itu memuatkan tendensi “kultus individu” akan gugur dengan sendirinya. Karena yang kita lihat di sana hanyalah “sejumlah ikon”; segalanya hanya menyimpan “kemiripan” semata. Tak ada yang benar-benar nyata.
Terus terang, adalah sungguh sangat sayang jika kita sampai harus kehilangan film garapan Arifin C. Noer itu. Terlepas dari “ideologi” apa yang menyelubunginya, sebagai sebuah karya seni, ia merupakan salah satu dari sedikit saja film kita yang mampu digarap dengan begitu apik dan sangat baik. Dengan kata lain, film itu (selalu) layak untuk tetap dinikmati.
Kalaupun adanya tendensi kultus individu masih tetap jadi persoalan besar yang mengganjal, dua usul “kompromis” dari seorang kawan yang sempat ia lontarkan dalam sebuah diskusi kecil dengan penulis mungkin bisa dipertimbangkan: (1) mereediting film itu, terutama pada bagian-bagian yang menggambarkan sosok tokoh Soeharto yang dianggap terlalu berlebihan, sehingga keberadaannya bisa menjadi lebih proporsional; dan (2) menghilangkan teks-teks indeks (nama tokoh, tempat, dan peristiwa) adar bisa lebih menjauhkan “realitas dalam film” dari “konteks faktual”-nya.
Memang akan menyimpan beberapa konsekuensi kalaupun kedua usul kompromis kawan saya itu diterima; film itu mungkin akan menjadi kehilangan “keutuhan dan orisinalitas”-nya, selain pertanyaan perihal siapa yang berhak memutuskan dan melakukannya pun (karena film itu karya Arifin, sementara Arifin sendiri sudah tiada) agaknya akan membuahkan persoalan pula. Namun demikian, usaha kompromis tersebut mungkin setidaknya akan bisa membuka peluang untuk menempatkan kembali film itu pada posi-sinya sebagai sebuah karya yang layak untuk hidup dan dinikmati, serta berkesempatan untuk berhadapan dengan semangat zaman dalam realitas kekinian yang harus dijejakinya.
Tentu, harapan terbesar yang muncul dalam Orde Reformasi kita hari ini sebenarnya adalah semua karya seni bisa hidup secara utuh dalam eksistensinya di tengah-tengah masyarakat luas, tanpa harus selalu merasa dihantui oleh kecemasan dan kabar-kabar buruk yang siap menikamnya. Sudah saatnya kini ia diberi kesempatan untuk berpijak sebagai dirinya sendiri, memiliki bargaining power, agar ia tidak lagi harus selalu menjadi “korban” sebagaimana yang kerap terjadi pada masa-masa sebelumnya.
²²²