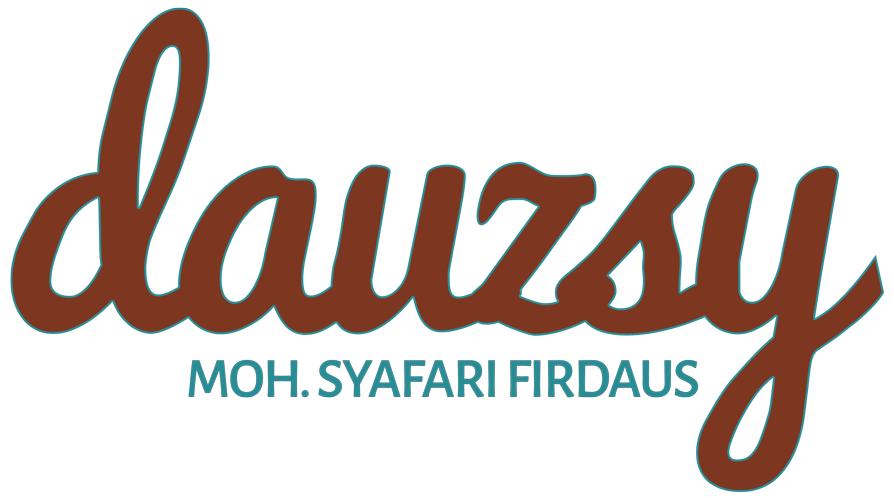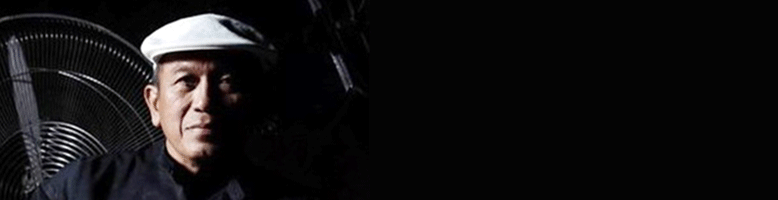Pementasan Yel, Putu Wijaya, Gedung Serbaguna ITB, 14 November 1995.
Dengan latar bentangan kain layar putih, panggung adalah pelataran gelap. Perlahan-lahan kesenyapan itu ditimpali instrumen Harry Roesli, selaku penata musik, dengan deraian suara-suara malam, jangkrik, kodok, nyanyian serangga-serangga kecil, dan suara sapuan angin berkibasan pelan. Tidak berapa lama, aroma keluar memenuhi udara. Ada kesan mistik di sana. Masih diiringi suara-suara itu, dari kanan-kiri panggung muncul sentilan cahaya kecil yang membersit dari ujung-ujung hio yang terbakar. Hio itu bergerak menjadi deretan kunang-kunang yang beterbangan, berkejaran, melingkar berputaran, bersentuhan sesamanya, dan panggung beberapa saat dihiasi gerak cahaya-cahayanya sebelum akhirnya bercak-bercak sinar itu terbang dan menghilang lagi entah ke mana.
Adegan sesaat yang cukup apik dan tenang tadi sungguh merupakan pembuka yang demikian kontras dengan adegan-adegan Yel karena sesaat kemudian suasana senyap itu dirobek dengan keriuhan yang mengiringi kemunculan siluet dua benda aneh. Benda itu seperti gada, yang satu bulat biasa lengkap dengan tangkai (ekor)-nya yang tampak aktif bergerak, sedangkan satunya lagi hanya tampak mata gadanya yang berduri dan pasif (tidak melakukan gerakan apa-apa. Secara sederhana, mungkin ini merupakan simbol yang digarap Putu Wijaya mengenai proses awal kelahiran manusia yang dalam sains diterangkan sebagai pertemuan sel telur dengan sperma.
Selain dari pandangan sains, tampaknya Putu mencoba untuk menarik dan menggabungkan hal ini dengan istilah Hindu tentang kejadian manusia pertama. Pada kitab Brahmananda Purana diterangkan bahwa setelah menciptakan surga yang indah, Brahma berkenan menciptakan para dewa, asura, pitara, dan manusia. Dalam semedinya, gemuruh, cahaya kilat, petir, pelangi, mega, kidung puji-pujian Weda, mantra, sesajen, telah ke luar pula dari tubuh Brahma sebelum kemudian tercipta binatang, tumbuhan, naga, jin, setan, raksasa, manusia, dan benda-benda serta makhluk lain yang mengisi jagat raya ini. Di sini, Putu tampak telah mengadopsi hal-hal tersebut gemuruh, cahaya-cahaya kelebatan kilat, petir, dan sekian nuansa warna yang dipadukan melengkapi permainan siluet di bentangan layar putihnya. Bahkan, Putu tampaknya ingin menggambarkan dan menonjolkan pula adanya suatu peperangan dahsyat yang terjadi di sana.
Jika menengok Upanishad, terutama ajaran Sankya, kita akan mendapati keterangan yang menyebutkan bahwa manusia yang lahir pada hakikatnya hidup dalam dua dunia: material dan spritual, jiwa (purusa) dan alam prakiti yang meliputi segala sesuatu yang berubah; bersifat nisbi. Prakiti sendiri terbagi lagi menjadi tiga unsur: satvva (unsur keselelarasan, terang, kesempuraan, dan kemurnian), rajas (unsur perkembangan, gerak, dan nafsu), dan tamas (unsur kegelapan, kelambanan, dan kemusnahan). Dari perpaduan dan kaitan ketiga unsur tersebut, terjadilah aneka bentuk yang dapat kita amati. Adapun purusa semuanya sama: tunggal dan tidak pernah terubahkan. Prakiti tercermin dalam purusa bagaikan sebuah kristal yang jernih (Zoetmoedler, Manunggaling Kawula Gusti, hlm. 92, dst.).
Jika kita melihat dalam konteks di atas, “peperangan” yang ditonjolkan Putu Wijaya akan terjadi disebabkan adanya jalinan dan pertentangan tiga unsur dalam dunia prakiti. Dalam simbolisasi yang diungkapkannya, dapat terlihat bahwa Putu merujuk pada hal-hal tersebut. Kehadiran raksasa yang memakan dan menghancurkan semua benda, bahkan melahap tempat-tempat ibadah, misalnya, dapat kita tarik sebagai simbolisasi unsur tamas.
Dalam upaya melenyapkan unsur tamas, manusia tentu harus berperang melawannya, tetapi nyatanya terkurung dan akhirnya justru dikuasasi unsur rajas, yakni hawa nafsu jasmaniah yang dalam pementasan ini digambarkan dengan manusia yang saling terkam dengan sesamanya. Ini terlihat pula dalam peperangan antara Prabu Kalakarna dan Raden Suryamaja (Adipati Karna) yang disebabkan Prabu Kalakarna jatuh cinta kepada Dewi Surtikanti dan Madukara yang kemudian diculiknya. Ini pun merupakan perwujudan dari kuatnya nafsu jasmaniah manusa yang terlihat pula pada adegan sanggama yang jabang bayinya lantas diaborsikan.
Dalam pementasan yang didominasi gerak ini, tampaknya Putu mencoba untuk memadukan unsur gerak dari tradisi Indonesia sendiri, sebagaimana permainan gerak siluet pada bentangan layar yang mengingatkan kita pada tradisi wayang kulit. Penghadiran wayang kulit itu sendiri diwakili oleh Prabu Kalakarna (wayang kulit) dan Adipati Karna (wayang golek), serta gerak enerjik serta dinamis dari kesenian Bali. Ini ditambah dengan gerak lain hasil adopsi tradisi luar seperti seni Kabuki Jepang yang kental mewarnai pementasan tersebut.
Untuk menampilkan sebuah kebulatan pementasan dengan keragaman masing-masing tradisi, tentunya dibutuhkan proses yang bukan hanya asal comot. Paling tidak, di sini dibutuhkan suatu pemahaman yang matang mengenai konsepsi dan latar belakang yang tersimpan pada masingmasing tradisi yang tentunya memiliki nilai estetis dan aspek filosofisnya sendiri.
Di sini, Putu dapat dikatakan berhasil dalam upaya melakukan penggabungan unsur gerak tersebut tanpa terkesan adanya keterpatahan, misalnya saat dia harus menyelaraskan unsur gerak Balinya yang enerjik dan dinamis dengan gerak Kabuki Jepang yang dapat dikatakan lamban. Hal ini terlihat pada adegan ketika seorang wanita yang membawa kipas (gerakan khas Kabuki) yang bunuh diri dan tubuhnya diangkat ke atas. Kita bisa melihat adanya sinkronisasi antara tradisi harakiri Jepang dan konsep Upanishad.
Hal ini setidaknya bisa menunjukkan bahwa Putu tidak semata-mata mengadopsi tradisi-tradisi itu untuk ditempelkan sekadar mengejar pencapaian estetis pementasannya. Masih ada suatu garis penghubung yang mengikatnya dan yang paling penting di sini pementasannya rasional, tidak absurd dalam keliaran imajinasi yang mengawang-awang tanpa kejelasan konsep.
Namun, sangat mungkin kesan keterpatahan ini menjadi tidak terasa karena ditunjang oleh penghadiran berbagai ungkapannya yang masih tampak sangat abstrak, surealis, dan tidak terbaca secara kasat mata. Ia masih merupakan sekumpulan gagasan yang memerlukan penerjemahan lebih lanjut dari penikmat dan penonton dramanya. Bahkan boleh jadi, karena terlampau banyak gagasan yang akan dituangkan dan diungkapkan, Putu pada akhirnya memilih untuk tidak banyak bicara. Ia hanya menampilkan gerak-gerak yang pada kenyataannya memang akan lebih mampu mengungkapkan yang mungkin tidak pernah dapat terwakilkan lewat kata-kata verbal. Fana tak terungkapkan dan nyata.
Maya menampilkan tiga aspek sejauh itu dapat dikenal oleh tiga macam pengetahuan, yakni pengetahuan tradisional, rasional, dan eksperimental, demikian salah satu ajaran Upanishad. Tampaknya, dalam pementasan Yel yang maya ini, Putu Wijaya mencoba untuk dapat menyentuh sekaligus menunjukkan ketiga pengetahuan itu sebagai dasar konsep estetikanya.***
Bandung Pos, 13 Desember 1995