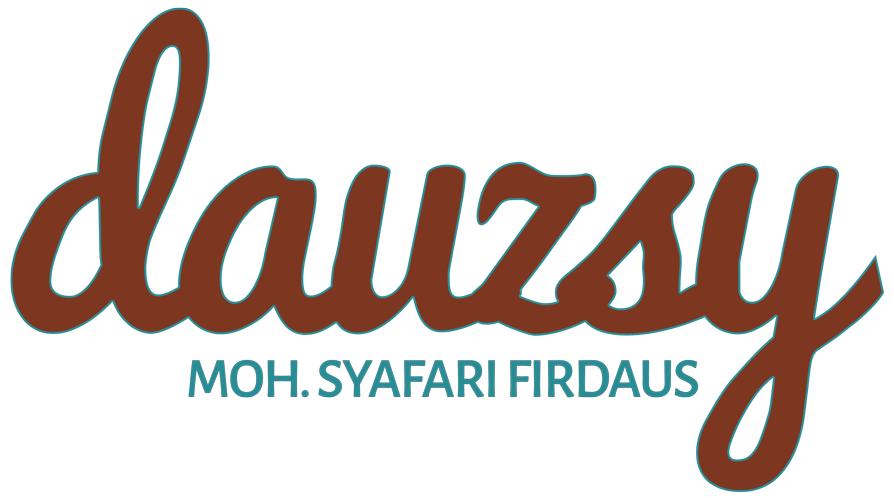“Hindia Timur”, yang kemudian dikenal sebagai Indonesia, ternyata memang cukup menakutkan: “Seperti juga Tuan tahu, cuma satu dari tiga orang yang pergi ke sana bisa kembali hidup-hidup.” Paling tidak, itulah yang menjadi kekhawatiran Eva sehingga dia merasa perlu untuk menutup-nutupi perbuatan Hakim Adam terhadapnya, yang telah merayunya dengan ancaman, Ruprecht, kekasihnya, akan diwajibmiliterkan ke Batavia.
Demikianlah, dari wacana “tentang Indonesia” di kamar Eva pada malam ketika Hakim Adam menginginkan sesuatu dari Eva, serentetan peristiwa pun kemudian terjadi: Ruprecht datang mendobrak pintu kamar, Hakim Adam gegas kabur meloncat jendela, sempat kena gebuk kepalanya sebelum jatuh di belukar rumpun anggur, meninggalkan luka, wig kehormatan, dan jejak langkah kaki bengkoknya pada tebaran salju di sepanjang jalan. Pada peristiwa di kamar Eva itu pula, sebuah guci bersejarah milik Ny. Martha telah pecah berantakan.
Pecahnya guci ini seterusnya menjadi pangkal pergunjingan: Ny. Martha tidak terima, dan menuntut keadilan untuk gucinya yang pecah itu. Dia lantas menunjuk Ruprecht sebagai pelakunya, menyeretnya ke pengadilan, meminta agar Ruprecht dihukum atas perbuatannya. Sementara, di balik meja pengadilan itu, duduk Hakim Adam yang memimpin jalannya sidang. Nah!
Ruang pengadilan itu sendiri—dalam lakon Guci yang Pecah karya dramawan Jerman Heinrich von Kleist yang dipentaskan Teater Sastra Universitas Indonesia di auditorium CCF Bandung, 23/11/2000—ditampilkan dalam bentuk procenium, dengan penataan sett yang tampaknya sengaja dimaksudkan untuk kepentingan aspek keseimbangan panggung: ada tungku perapian dan gantungan baju yang ditempatkan di bagian tengah—belakang; dua buah kursi panjang yang dipersiapkan bagi mereka yang beperkara dan sebuah kursi bersandaran tinggi untuk Hakim Tinggi Walter (yang dalam cerita ini, datang sebagai seorang utusan dari pusat untuk menginpeksi kinerja pengadilan yang dipimpin Hakim Adam) ditempatkan di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya tersimpan dua pasang meja—kursi yang masing-masing adalah milik Hakim Adam dan Panitera Licht. Di salah satu sisi ruang itu pun, tepat bersebelahan dengan tungku perapian, ditampakkan seonggok kasur tempat Hakim Adam tidur. Ini cukup mengherankan. Dengan penempatan kasur ini, “logika ruang” serta merta menjadi goyah, bahkan mentah, dibuatnya: ruang (pengadilan) macam apakah gerangan?
Adegan dibuka selepas para pemain musik menyelesaikan sebuah lagu pengiring. Di panggung, Hakim Adam tampak tengah terbaring, masih tidur di kasurnya, dengan wajah dan kepala botaknya yang penuh luka. Dalam tidurnya itu, ada gerakan-gerakan “komedian” yang dibuatnya. Entah, mungkin untuk sekadar memancing senyum atau tawa; atau mungkin juga untuk memberi indikasi awal jika pertunjukkan yang disutradarai oleh I. Yudhi Sunarto ini akan disuguhkan dalam semacam “gaya komikal/karikatural”. Selebihnya, sesaat setelah Hakim Adam bangun dan para tokoh lainnya bermunculan, lakon tragik-komedi karya Kleist yang sederhana, namun sangat detil dan tampak begitu mementingkan aspek kausalitas (kaitan logis) antarperistiwa ini, mulai bergulir.
**
Secara keseluruhan, pementasan yang berdurasi sekitar 140 menit itu, boleh disebut, lumayan cukup “menghibur”, meskipun masih jauh untuk bisa disebut mengesankan sebagai sebuah pertunjukkan teater. Di awal-awal pertunjukkan, permainan bahkan cenderung menjemukan. Dialog yang terjadi antara Hakim Adam dan Panitera Licht, misalnya, sering hambur begitu saja, seakan hanya keluar dari bentuk hapalan, yang pada akhirnya tidak bisa “ditandai” ataupun “menandai”. Demikian pula dengan pengambilan moving dan blocking yang dipilihnya: terlalu “cerewet”, banyak yang mubazir, bahkan terkesan “tidak sadar ruang”.
Pilihan Yudhi Sunarto untuk mengemas Guci yang Pecah dalam “gaya komikal/karikatural”, dipandang dari perspektif tertentu memang menawarkan sesuatu yang menarik. Paling tidak, yang bisa terbaca, Guci yang Pecah karya Kleist yang tragik-komedi ini kiranya tetap dipandang dalam kerangka “komedian” dan disikapi dengan cara “yang ringan dan yang lucu”. Akan tetapi, pilihan ini pun tentu saja akan mengandung sejumlah konsekuensi, di tingkat (teknis) pemanggungan terutama, setidaknya, agar pementasan bisa terjauh dari kesan “ala kadarnya”.
Sementara, dari sudut pandang lain, boleh jadi pilihan ini jatuh dengan suatu kesadaran agar bisa menyiasati sejumlah kelemahan di tingkat keaktoran dan teknis pemeranan; meski untuk penyiasatan itu pun tidak lantas mengartikan, soal-soal yang berkaitan dengan keaktoran dan teknis pemeranan pada akhirnya bisa diabaikan untuk seterusnya mengharapkan sejumlah pemakluman. Tanpa adanya kesiapan dan juga penyiasatan yang tepat dalam soal ini, pilihan pa-da “gaya komikal/karikatural” yang tadinya tampak sederhana itu, pada akhirnya justru akan berbalik menjadi cukup menyulitkan: gamang dan terseok-seok.
Sayangnya, kondisi demikian kiranya terjadi pada Guci yang Pecah garapan Yudhi ini: apa yang ditawarkannya terkesan menjadi bertipikal serba tanggung. Di satu sisi, Yudhi tampak masih ingin mempertahankan “kecerdasan teks” yang disodorkan Kleist, namun di sisi lain ia seakan tidak terlalu percaya pada kecerdasan komedi di tingkat tekstual sehingga merasa tetap perlu “dibantu” oleh para aktornya untuk berkomedi juga. Hanya celakanya, yang kemudian terjadi di panggung, para aktor kerap terjebak untuk selalu bermain dengan stilisasi yang tampak dibuat-buat, mengalami banyak pengulangan, dengan gestulasi-gestulasi komedian yang cenderung slapstik (Hakim Adam, Panitera Licht) dan terlalu hiperbolik (Margareth, Liza, polisi).
Boleh jadi, ini adalah satu implikasi dari penyiasatan yang tidak tepat dalam soal-soal yang berkenaan dengan pemeranan. Bisa cukup jelas terlihat, para aktor tampak bermain hanya dalam kapasitasnya sebagai pemain, tanpa terlihat ada semacam usaha untuk “berperan—menjadi” ketika mereka dituntut untuk memasuki wilayah peran yang harus dimainkannya. Mereka sering kehilangan karakter (peran) ketika mereka berusaha untuk saling menyikapi satu sama lain.
Hakim Adam (Rahardian Adetya), misalnya, kerap kehilangan motif, baik ketika ia mengartikulasikan dialog maupun dalam pilihan move yang kemudian diambilnya. Belum lagi dengan gestulasi: Rahardian tampak benar tidak konsisten dalam soal kaki bengkok Hakim Adam yang kontinyuitasnya sungguh signifikan untuk diperhatikan. Di tingkat pemeranan ini, praktis hanya pemeran Ny. Martha (Sri Muniarti) dan Ruprecht (Wisnu Surya Pratama) yang kiranya masih bisa dipandang cukup loyal dalam mengusung perannya, yang sekaligus menjadi obat penawar yang melegakan.
Keserbatanggungan ini pun tampak juga dalam garapan artistiknya. Ikon-ikon Eropa yang ingin dihadirkan lewat sejumlah sett dan properti, kiranya tidak mendapatkan aktualisasinya secara penuh di atas panggung: tungku perapian yang tampak dipersiapkan dengan serius, misalnya, menjadi kehilangan daya aksentuasinya ketika keberadaannya disandingkan dengan meja—kursi yang tidak terlalu meyakinkan ke-“eropa”-annya. Begitu pun dengan kursi yang ditempati oleh Hakim Tinggi Walter. Boleh jadi, kursi bersandaran tinggi ini adalah milik tuan rumah, yang mungkin biasanya dipakai oleh Hakim Adam.
Akan tetapi, eksistensi kursi ini menjadi kabur untuk bisa diidentifikasi lebih lanjut ketika tidak tampak ada penyikapan yang jelas untuknya. Yang justru terlihat, kehadiran kursi yang telah ada di atas panggung dari semenjak awal pementasan itu (ketika Hakim Tinggi Walker datang kursi itu hanya dipindahtempatkan), seolah-olah memang hanya dipersiapkan untuk Hakim Tinggi Walker.
Mungkin ini tampak sepele, meskipun kemudian harus berbuah implikasi pada penandaan, kursi tersebut seolah-olah telah dipersiapkan bahkan sebelum ada seorang pun (di pengadilan itu) mengetahui bahwa Hakim Tinggi Walker akan datang! Kekurangcermatan yang kehilatan sepele ini pada akhirnya menjadi sungguh ironis, karena naskah yang dipentaskannya justru begitu mementingkan aspek kaitan logis.
Kalaupun sampai harus jatuh suatu penilaian, terus terang, pementasan ini sebenarnya terselamatkan oleh Kleist lewat naskahnya, Guci yang Pecah (hasil terjemahan I. Yudhi Soenarto/Ekkehard Zeeb; sementara naskah lakon ini pun sempat diterjemahkan/diadaptasi oleh Suyatna Anirun dengan judul Jambangan yang Pecah), yang memang menawan; terlebih jika membaca paparan yang diberikan Ekkehard Zeeb, dalam kapasitasnya sebagai dramaturg, seperti yang termuat dalam booklet pementasan.
Pada konteks peran dramaturg itu pun, yang patut disayangkan, keberadaan Zeeb kelihatannya tidak terlalu banyak membantu. Dalam kapasitasnya sebagai dramaturg, catatan Zeeb yang cukup komprehensif itu kiranya “masih terlalu cerdas” bagi wujud pementasan ini: gagasan-gagasan tekstualnya (mengenai mitos, bahasa, komedi) nyaris tidak ditemukan di atas panggung. Mungkin bisa dimengerti, karena gagasan-gagasan tekstualnya itu tampaknya memang praktis tidak akan mendapatkan tempat untuk bisa “meruang” di atas sebuah panggung yang serba tanggung.
***